Pameran lukisan Endih Baturan : Dari Leak Hingga Rohingya
Foto suasana pameran lukisan Endih Baturan yang digelar dalam “Pesta Kesenian Bali” (PKB) ke-40, yang berlangsung dari tanggal 23 Juni hingga 21 Juli 2018
KEGIATAN melukis atau menggambar di Desa Batuan, Gianyar, Bali, telah ada sejak zaman kerajaan Bali kuno dan menjadi bagian dari ritual keagamaan. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya kata “citrakara” (ahli gambar) dalam Prasasti Batuan yang dibuat tahun 944 Saka (1022 M) pada masa pemerintahan Raja Marakata dari Dinasti Warmadewa.
Namun, seni lukis gaya Batuan menemukan eksistensinya dan semakin dikenal luas ketika dikoleksi dan dipromosikan oleh antropolog Margaret Mead dan Gregory Bateson yang melakukan penelitian di sana pada pertengahan tahun 1930-an. Pada masa itu, lukisan Batuan banyak menampilkan tema kehidupan sehari-hari, cerita rakyat, mitologi, dan cuplikan kisah pewayangan, dengan nuansa magis yang sangat kental.
Seni lukis gaya Batuan mampu bertahan dan berkembang hingga sekarang karena adanya sistem pewarisan pengetahuan dan keterampilan melukis dari generasi ke generasi. Sistem itu dulunya bersifat informal dan berlangsung dalam keluarga atau lingkungan terdekat. Metodenya pun berbeda-beda. Ada dengan cara meniru atau mencontoh. Ada dengan memberikan teori atau teknik, kemudian murid mencari dan mengembangkan sendiri tema yang disukainya.
Salah satu pelukis Batuan yang sangat idealis dalam mengajar murid-muridnya adalah I Nyoman Ngendon (1906-1946). Bagi Ngendon, setiap murid harus mampu menggambar bentuk-bentuk yang berbeda. Ngendon melahirkan generasi pelukis Batuan yang mampu menggali dan mendalami tematik secara kuat. Sementara itu, pelukis lain yang tidak berguru pada Ngendon, cenderung berkutat dengan tematik tradisional.
Teknik melukis gaya Batuan sangat rumit, mengandalkan keterampilan, kesabaran, dan ketekunan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni membuat sketsa (ngorten), memberi kontor pada sketsa (nyawi), membuat gradasi secara bertahap (ngucek), menampilkan kesan kedalaman dan membuat fokus tertentu (manyunin dan ngidupang), dan memberi warna (ngewarna). Teknik yang rumit itu menyebabkan pelukis Batuan memerlukan waktu relatif lama untuk menyelesaikan sebuah lukisan.
Pada “Pesta Kesenian Bali” (PKB) ke-40, pelukis dari Desa Batuan yang tergabung dalam Komunitas Pelukis Baturulangun diberi kesempatan memamerkan karya-karyanya. Pameran ini melibatkan 36 pelukis lintas generasi. Semua lukisan dibuat dengan ukuran yang sama, yakni 70 x 50 cm. Selain lukisan, pameran ini juga menampilkan sebuah karya instalasi yang dibuat secara berkelompok. Pameran akbar ini bertajuk “Endih Baturan: Membaca Kedalaman Seni Lukis Batuan”, menyesuaikan dengan tema besar PKB: “Teja Dharmaning Kauripan, Api Spirit Penciptaan”.
Kata “endih” mengacu kepada nyala, api, cahaya, aura. Endih seringkali dikaitkan dengan perwujudan leak, ilmu mistik dari Bali. Biasanya, orang-orang yang menekuni ilmu kebatinan, sastra, ataupun kesenian, akan memancarkan endih (aura) yang kuat dari batinnya. Itulah yang membedakannya dengan orang kebanyakan. Dalam konteks pameran ini, “Endih Baturan” bermakna “Cahaya dari Baturan”, mengacu kepada kedalaman, kekuatan, dan keunikan seni lukis gaya Batuan. Kata “Baturan” sendiri mengacu kepada nama lain Desa Batuan pada masa kerajaan.
Tiga puluh enam pelukis yang menampilkan karyanya dalam pameran ini berasal dari generasi tua maupun muda. Yang paling tua adalah I Made Tubuh (1942) dan termuda adalah I Made Adi Sumarjaya Putra (2000). Dari perbedaan generasi ini sekilas kita bisa melihat dan menilai bagaimana perkembangan dan pertumbuhan seni lukis gaya Batuan. Secara umum, generasi tua sangat kuat mempertahankan teknik, visual, dan konten seni lukis gaya Batuan. Nuansa magis masih terasa kental pada karya-karya mereka.
Dalam pameran ini, tema api tidak hanya dimaknai secara harfiah. Namun, api juga menjadi metafora atau simbolisasi, terkait spirit penciptaan, olah batin, untuk menghasilkan suatu karya yang memesona dan membuka ruang renung bagi banyak orang. Api di dalam diri dan api di luar diri menjadi suatu keterkaitan yang bisa dimaknai dengan berbagai cara. Dalam konteks pameran ini, penafsiran dan pemaknaan api menjadi sangat beragam.
Pelukis Batuan sudah terlatih dan terbiasa melukis cuplikan kisah yang bersumber dari pewayangan, mitologi, cerita rakyat, dan kehidupan sehari-hari. Hal itu seolah sudah menjadi pakem bagi lukisan mereka. Maka, tak heran, beberapa pelukis memetik tema api dari sumber-sumber tersebut. Hal itu, misalnya, bisa dilihat pada lukisan I Ketut Murtika yang mengisahkan Hanoman membakar Alengka dengan api yang menyala di ekornya. Atau, pada lukisan Wayan Eka Mahardika Suamba yang menampilkan kisah Drupadi yang lahir dari api berkat tapa brata Prabu Drupada. Tema api yang diambil dari mitologi, cerita rakyat, dan pewayangan juga muncul pada lukisan I Made Tubuh, Nyoman Toya, Ketut Jaman Suarnawa, Sumarjaya Putra, Nyoman Kastawan, Nyoman Sudirga, Ketut Kenur, I Gusti Ngurah Muryasa, Ketut Balik Parwata.
Selain pewayangan, pada masa lalu cerita leak cukup banyak mendominasi lukisan gaya Batuan. Hal itu pula yang membuat lukisan Batuan sangat kuat dengan nuansa magisnya. Leak dan endih (api mistik) juga muncul dalam pameran kali ini. Misalnya, bisa dilihat pada lukisan Nyoman Marcono yang menampilkan adegan proses manusia sakti berubah wujud menjadi leak. Atau, pada lukisan Nyoman Nurbawa dan Ketut Wirtawan yang mengisahkan cuplikan cerita Calonarang, adegan adu kesaktian membakar pohon beringin yang dilakukan oleh Mpu Bradah dan Dirah, penguasa ilmu hitam yang sangat ditakuti.
Beberapa pelukis mengaitkan tema api dengan cerita kehidupan sehari-hari, pariwisata, ritual, dan pentas kesenian. Hal itu bisa dilihat pada lukisan I Gusti Ngurah Agung, Wayan Naka, Wayan Dana Wirawan, Nyoman Selamet, Made Nyana, Ketut Reta, Made Renata, Dewa Wirayuga, Dewa Nyoman Sudiana, Dewa Nyoman Martana, Pande Made Martin, Ida Bagus Putu Padma, Wayan Budiarta, Made Griyawan, Made Sujendra. Masing-masing berusaha memunculkan ikon api sesuai dengan pemahaman dan penafsiran mereka terhadap tema yang dilontarkan panitia PKB. Yang menarik, dengan penafsiran kritis, Wayan Malik menampilkan lukisan tentang penebangan dan pembakaran hutan yang bisa dikaitkan dengan wacana ekologi dan pemanasan global.
Di sisi lain, Wayan Warsika mengaitkan tema api dengan kenangan kelam masa silam. Dia tidak menggali tema api dari cerita pewayangan atau mitologi. Dia melukis dari ingatannya tentang peristiwa kerusuhan dan kekerasan yang terjadi pada tahun 1960-an di Desa Batuan. Saat itu, api dipakai untuk membakar rumah penduduk. Api amarah berkobar menjelma teror, ketakutan, dan kengerian.
Agak berbeda dengan api dalam lukisan I Ketut Sadia yang berjudul “Spirit Para Pengungsi”. Sadia juga tidak memetik tema api dari cerita pewayangan maupun mitologi, namun dari perenungannya tentang tragedi kemanusiaan yang mengusik hatinya. Dia tidak secara khusus melukis tentang api, namun perahu-perahu yang dipenuhi pengungsi Rohingya yang sedang menyelamatkan diri dari konflik etnis. Matahari pagi dalam lukisannya adalah simbol cahaya (api) harapan yang memberi semangat pada jiwa yang redup untuk meraih suatu kehidupan baru yang bebas dari segala bentuk pertikaian dan kekerasan.
Api sebagai simbol juga bisa dilihat pada lukisan “Sinar Seorang Pemimpin” karya Wayan Diana, menampilkan seorang gembala yang tubuhnya memancarkan cahaya (aura). Gembala adalah simbol pemimpin dan sapi adalah simbol rakyat jelata. Seorang pemimpin seharusnya memiliki aura jiwa kepemimpinan sehingga mampu menerapkan pemerintahan yang adil dan bijaksana.
Ilmu pengetahuan adalah api yang bisa menjadi pelita untuk menerangi kegelapan pikiran. Hal itu diungkapkan secara simbolik oleh I Gede Widyantara lewat lukisan berjudul “Cahaya Api Ilmu Pengetahuan”. Dan, untuk mencapai pikiran yang terang tentu tidak cukup dengan ilmu pengetahuan. Segala sifat bhuta (energi negatif) dalam diri manusia mesti dilebur, seperti yang ditampilkan secara simbolik dalam lukisan Made Karyana yang berjudul “Pralina”.
Pengolahan tematik dan visual secara unik ditampilkan oleh Wayan Aris Sarmanta lewat lukisan berjudul “Jiwa On Fire”. Lukisannya membuka ruang renung tentang api yang bersemayam dalam jiwa, yang bisa menjadi api semangat atau sebaliknya menjadi api amarah. Manusia harus mampu mengendalikan api dalam dirinya agar selamat menjalani kehidupan. Secara visual, lukisan Aris termasuk anomali dalam seni lukis gaya Batuan yang nyaris seragam. Dengan menggunakan teknik melukis gaya Batuan, dia mengolah dan menampilkan visual yang cenderung kontemporer.
Di tengah gempuran modernisasi yang melanda Desa Batuan, pameran ini membuktikan bahwa seni lukis gaya Batuan masih tetap tumbuh dan berkembang. Selain itu, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam seni lukis gaya Batuan telah diwariskan secara masif kepada generasi baru melalui program pelatihan melukis bekerjasama dengan beberapa Sekolah Dasar di Desa Batuan. Upaya-upaya pelestarian dan pengembangan ini sangat memungkinkan untuk menjadikan seni lukis gaya Batuan sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Dengan demikian, api spirit penciptaan senantiasa menyala dari generasi ke generasi.***
Penulis : Wayan Jengki Sunarta
Sastrawan dan penulis seni rupa



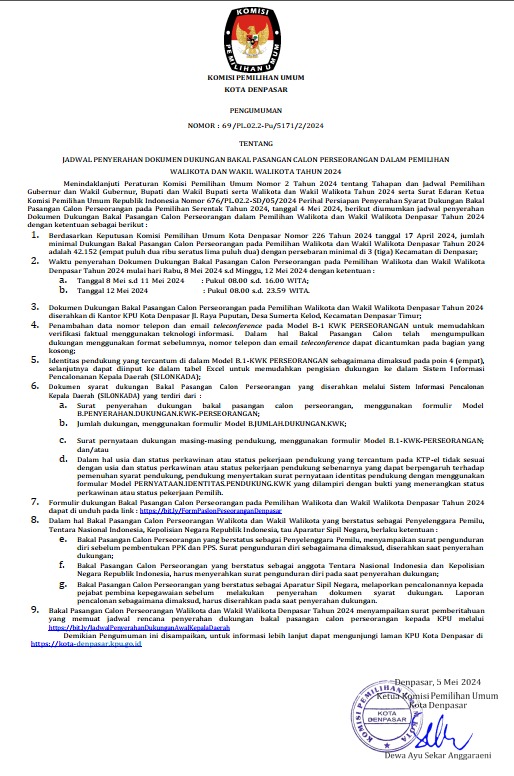









Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.