MEA Sebentar Lagi

Jakarta (Metrobali.com)-
Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lebih satu dekade lalu sepakat membentuk pasar tunggal pada 2015 dalam upaya agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing.
Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
Pembentukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang diistilahkan dengan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan makin ketat.
ASEAN beranggotakan sepuluh negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam.
MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, dan akuntan.
Pelaksanaan MEA yang sudah dalam hitungan bulan ini berarti pertarungan terbuka di bidang ekonomi antar-anggota ASEAN sebentar lagi berlangsung.
Apakah penyatuan ekonomi di kawasan ini merupakan peluang atau ancaman bagi Indonesia? Siapkah Indonesia? Sudah banyak yang mengingatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton saat pasar bebas itu berlaku. Menjadi penonton bisa diartikan bahwa pasar nasional hanya menjadi pasar negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu.
Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan efisiensi, daya saing, nilai tambah, dan juga produktivitas dari beragam kinerja perekonomian di berbagai daerah di Tanah Air.
Siapkah Indonesia? Indonesia seharusnya siap dengan pelaksanaan MEA tersebut karena memang sudah terlibat dari awal pembicaraan mengenai kesepakatan liberalisasi bidang perdagangan, investasi, jasa, tenaga terampil dan arus modal di kawasan itu.
Namun, perbedaan pendapat, khususnya berkaitan dengan kesiapan, masih berlangsung. Jika dicermati perbedaannya mencolok.
Banyak pengamat serta pelaku industri dan jasa menyatakan khawatir dengan kesiapan Indonesia karena banyaknya masalah yang masih dihadapi, sementara pemerintah hanya menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam memanfaatkan kesepakatan itu.
Kalangan yang khawatir menilai industri nasional belum bisa bersaing dengan produk negara anggota ASEAN yang lain karena pengembangan industri nasional masih terkungkung sejumlah hambatan yang justru dari dalam negeri sendiri.
Hambatan itu antara lain berupa kondisi infrastruktur yang tidak memadai sehingga membuat biaya logistik tinggi, tarik ulur masalah ketenagakerjaan, hingga masalah maraknya pungutan liar hingga izin birokrasi yang berbelit.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengingatkan bahwa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit dengan perjanjian pasar bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA).
“Pengalaman pahit dengan ACFTA menunjukkan bahwa industri Indonesia tidak siap sehingga pasar dalam negeri banjir barang dari Tiongkok,” kata Suryo Bambang Sulisto.
Menurut Suryo, setelah ACFTA telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini, industri Indonesia tidak juga menunjukkan kemajuan.
Ia mengingatkan, berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009, total impor Indonesia berjumlah 96,829 miliar dolar AS, terdiri atas bahan baku dan penolong sebesar 69,638 miliar dolar AS, barang modal 20,438 miliar dolar AS, serta barang konsumsi 6,752 miliar dolar AS.
Sedangkan pada 2013, total impor 186,631 miliar dolar AS terdiri dari bahan baku dan penolong 140,126 miliar dolar AS, barang modal 31,534 miliar dolar AS, serta barang konsumsi 13,139 miliar dolar AS.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan perubahan yang bersifat struktural dalam kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan manusia,” katanya.
Perubahan struktural itu, ujar dia, hanya akan terlaksana melalui kebijakan publik yang efektif, yang berarti perubahan mendasar juga diperlukan di bidang politik serta bidang birokrasi.
Ukur Kekuatan Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta mengatakan, perlunya Indonesia mengukur kekuatan dalam rangka menghadapi pemberlakukan kesepakatan tersebut pada 2015.
Politisi PDI Perjuangan itu mengulas, berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), dari sisi daya saing di 2013-2014 Indonesia berada pada peringkat 38 dari 150 negara yang disurvei.
“Peringkat daya saing ini makin baik. Tapi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan regional seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam ternyata kita masih di bawah negara-negara tersebut,” kata Arif Budimanta.
Dia menyampaikan menurut laporan WEF, penyebab daya saing Indonesia masih di bawah negara-negara di kawasan antara lain persoalan infrastruktur yang jauh tertinggal, persoalan efisiensi tenaga kerja, fakta bahwa Indonesia memiliki pasar jauh lebih besar dari negara-negara tersebut, serta terkait dengan penyebaran pasar keuangan yang masih lebih rendah disbanding negara-negara tersebut.
Arif mengatakan apapun tantangannya, kesepakatan MEA 2015 harus menjadikan masyarakat Indonesia lebih sejahtera dan lebih makmur sesuai diamanatkan UUD 1945.
Karena itu, dia menilai pemerintah perlu memperbaiki daya saing tenaga kerja, mengembangkan skema perlindungan konsumen seiring dengan bebasnya arus barang melalui penerapan standarisasi produk, serta mengembangkan skema perlindungan terhadap usaha nasional dengan kebijakan fiskal berupa insentif atau disinsentif.
Selain itu pemerintah perlu meningkatkan daya saing Indonesia mulai dari perbaikan infastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar tenaga kerja, penyediaan teknologi, pemerataan ekonomi dan proses pembangunan.
Mungkin tugas berat pemerintah baru mendatang setelah memutuskan kelangsungan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam APBN 2015 adalah mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi MEA. AN-MB



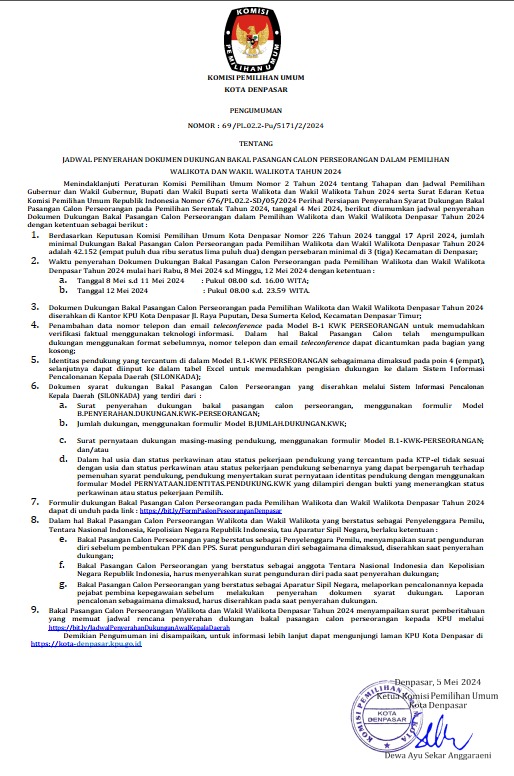









Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.