Siwaratri, Janji dari Tanakung
Ilustrasi
Denpasar, (Metrobali.com)
Maṅkānugraha saṅ hyan Iśwara sinémbahakén ikaṅ anāma Lubdhaka/
atyantéki meṅen-meṅnya tékap iṅ paramawara paweh hyan Iśwara/
tuștāmbéknya -n amiśra dewa tuwi tan papahi lawan awak Jagatguru/
maṅgeh kāraṇa niṅ samaṅkana sakéng brata Śiwarajani ndtan kalen//
Begitulah anugerah Hyang Siwa diterima Lubdhaka/ ia amat gembira menerima berkah utama itu/ hatinya senang bisa menyatu dengan Siwa, sementara dewa sekalipun tak sepadan dengan Siwa/ semua itu didapat setelah ia dengan tekun melaksanakan brata Siwarajani//
Ada kisah yang selalu menyita perhatian kita saat Sasih Kapitu tiba, kisah yang menggetarkan atas seorang pemburu bernama Lubdhaka. Beradab-abad silam, Mpu Tanakung, seorang pujangga Jawa tersohor mengabadikan kisah ini sebagai jalan pembebasan [mukta-ṅ kleśa siluṅluṅanya muliheṅ nirāśraya juga. Berharap bebas dari segala penderitaan, bekal pulang menuju pembebasan]
Lepas dari misi dan ideologi Siwaistis Hindu Jawa—kisah ini tampak menyita permenungan demikian dalam, dan hingga hari ini mendapat perhatian besar sebagai malam peleburan papa, yang lazim disebut ‘malam Siwa’ atau Siwaratri. Dan pemeluk Hindu Bali menyambut hari suci ini dengan penuh gairah, amat semarak.
Mpu Tanakung-lah yang membentuk momen penting ini— setidaknya setelah Hindu Majapahit membangun tata kehidupan baru pada keyakinan rakyat Bali. Tanakung yang hidup sezaman dengan raja Sri Adisuraprabawa dari era Majapahit akhir menampilkan kisah ini begitu dramatis, didaktis, sekaligus memesona. Dengan medium bahasa Jawa Kuna, Tanakung seperti membangun telaga baru bagi zaman yang kian suram saat itu.
Sebagaimana diyakini para penganut Siwa, barang siapa yang dengan sadar menggelar Brata Siwaratri dengan ketangguhan puncak, segala kepapaan akan dilebur menunju pembebasan puncak. …sapapa nika śirna denikaṅ brata ginawe akennya.
Untuk capaian puncak ini, Tanakung tidak menghadirkan tokoh yang tangguh dalam yoga. Sebaliknya ia menghadirkan seorang memburu yang nyaris tidak pernah berbuat kebaikan, yang kerjanya hanya membunuh dan membunuh, pemburu pemakan daging.
Demikianlah, tepat di hari keempat belas paruh bulan gelap sasih Kapitu, disertai hujan gerimis, pagi-pagi sekali Lubdhaka pergi berburu. Memakai baju biru kehitam-hitaman, membawa serta tombak, busur, dan panah Lubdhaka pergi seorang diri.
Perjalanan demikian jauh ke arah timur laut, dinaungi mendung dan gerimis pagi Sasih Kapitu. Melewati taman, dataran, kahyangan, pertapaan, bihara, yang sangat menawan hati. Tegalan luas di kaki gunung, beraneka tanaman di lerengnya. Air terjun memesona. Bangunan-bangunan tampak asri, atap pondoknya diliputi kabut dan gerimis. Asap mengepul, menari-nari di udara hendak menyatu dengan langit. Di bawah terlihat pohon beringin nan rimbun, seonggok balai berdinding tempat orang berunding.
Di sebelah barat ada dataran tinggi dengan huma luas, kebun-kebun subur dengan tanaman teratur rapi, dikitari pohon kelapa tengah disaput kabut. Burung kuntul terbang terkelap-kelip di tengah awan, seakan-akan hilang ditelan mendung karena tidak lagi tampak. Terlihat pertapaan para pendeta, pintu gerbangnya tinggi dan tembok pagarnya lurus. Pohon tanjung, cempaka, banah, nagasari tengah berbunga harum.
Di tengah-tengah kabut dan musim hujan Sasih Kapitu, Lubdhaka menyaksikan pemandangan menyesakkan. Bangunan tinggi tempat pemujaan rusak berat. Cabang penyangga berbentuk supit urang runtuh tak ada yang memperhatikan, temboknya rebah. Bangunan di halaman roboh, dan jalanan sepi. Atapnya berjatuhan tak dihiraukan orang, tiangnya condong tak karuan. Tampak ukiran di tembok bagai gadis perawan menatap langit, sungguh memilukan hati. Seperti menuturkan sakit hati karena lama tak ada pujangga menghampiri.
Lewat tokoh Lubdhaka, Mpu Tanakung seakan mengabarkan tanda-tanda zaman, “keruntuhan” sebuah keyakinan, merosotnya semangat ketuhanan. Pelukisan ini dengan mudah dapat kita simak dari penggambaran buram yang memilukan dari Kakawin Siwaratrikalpa.
Dengan wirama Ragakusuma misalnya; Tanakung menggambarkan sebuah Pura yang tak lagi dihiraukan. Sebuah persada puncaknya yang tinggi ditumbuhi rerumputan. Bagian tengahnya retak ditumbuhi pohon prih, rerimbunan pohon menaungi, semua palinggih rusak dibelit pohon-pohon melata. Begitu banyak bangunan suci hancur, saluran airnya tersumbat, taman-tamannya tidak lagi terawat.
Apa yang kita baca saat Mpu Tanakung menghadirkan tanda-tanda zaman seperti itu? Apakah ini gambaran awal dari senja kala Majapahit, di mana masyarakat tak lagi hirau pada dewa, tempat sucinya dibiarkan tak terawat, di sana-sini yang terlihat cuma balai-balai dan prasada yang rubuh, sepi tak ada pengunjung. Atau Tanakung tengah menangkap masyarakat Majapahit berangsur pindah keyakinan? Atau, apakah Tanakung ingin menggenapi kecemerlangan Mpu Tantular yang menulis Kakawin Sutasoma bernapaskan Buddha? Kita tidak tahu semua ini.
Jika benar Kakawin Siwaratrikalpa ditulis di masa akhir Majapahit, gambaran buram itu tampak benar adanya. Dan karenanya Tanakung berusaha menghidupkan kembali semangat keagaamaan itu dengan menulis kakawin sembari memuliakan kesucian Siwa sebagai maha pelebur kepapaan. Di tengah-tengah kekeringan zaman yang senja, Tanakung seakan menjajikan surga masa depan. Dan betul, sampai detik ini, di tempat ini, di Pura Lokanatha yang indah kita masih mengorek-ngorek titipannya, mendiskusikan sepenuh gairah.
Bahwa, dalam keyakinan Siwaistis, pembebasan itu akan ditemukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang paling hina dina sekali pun. Bila Lubdhaka, orang yang paling papa akhirnya mendapat surga, yang tanpa sengaja melakukan brata Siwa di malam Siwa, ia pun akhirnya terbebas. Dewa-dewa menjemput rohnya saat kematian.
Bagi kita Tanakung telah melahirkan peradaban spiritual dengan magnitud besar, tradisi yang tak mudah lekang digerus zaman. Sekian abad setelah keruntuhan Majapahit, tradisi spiritual yang dilahirkannya hidup terus di benak para generasi. Namun tanda-tanda zaman yang digambarkan Tanakung setidaknya mesti dibaca kembali, demi membaca tanda-tanda hari ini– karena toh betapa sering di zaman yang serba mudah, berlimpah, hidup dibuat sering lebih garing, dibekuk tamas kenikmatan-kenikmatan rendah. Dan manusia jadi lupa sang muasal.
Bila Tanakung menukilkan gambaran buram tentang tanda-tanda zaman yang rapuh, candi-candi roboh, tak ada mengunjung yang datang ke tempat suci, jalanan sunyi — lalu apa yang mesti kita baca dari kesemarakan beragama di Bali? Pura-Pura kita megah, terawat dengan bagus, pamedek nyaris tak pernah sepi, busana kita amat bersih, wangi dan rapi, sembari menggengam ponsel tercanggih, lalu apakah ini tanda sebuah kebangkitan rohani? Sungguh sulit mengukur dengan parameter apapun, kecuali kita menjadi makin sadar dan bahagia, dan lagi-lagi, ini tak mudah dikur dengan hitungan statistik pula.
Tapi apapun itu, Tanakung tetap memberi harapan, malah sebagai pemuja Siwa ia memberi janji, bagi siapa pun yang melakukan brata Siwaratri dengan tekun, setidaknya ia mendapat ‘pembersihan” jiwa, nun yang lebih utama tentulah pembebasan lahir batin. Karena di titik ini, Siwa seakan memberi pemenuhan, bahwa seorang papa pun akan terbebas dari segala belengu dunia. “tesam papani pasyanti Śiwaratri prajagarat,” demikian disuratkan kitab Padmapurana.
Kitab Wrehaspatitattwa malah memberi realisasi amat terang bagaimana seorang papa bisa terbebas dari kepapaannya. Di situ dalam dialog Hyang Siwa pada Bhagawan Wrehaspati, realisasi itu dipaparkan begini: ….yan maturtur ikaṅ ātma ri jatinya, irika yaṅ alilang, sang ātma juga umidépa saka suka duka niṅ śarira. ..jika atma sadar tentang jati dirinya, di situ lenyap[segala kepapan], sang roh sadar akan suka-duka dibelengu tubuh.
Ada tiga brata inti wajib dilakukan dalam upacara Siwaratri. Tiga brata itu meliputi; Mona [diam, tidak berkata-kata], Upawasa [tidak makan minum], dan Jagra [tidak tidur dilakukan selama 36 jam, mulai dari pagi hari pada panglong ke-14 sampai pada senja hari panglong ke-15]. Sedangkan Mona dan Upawasa dilakukan selama 24 jam, mulai dari pagi hari panglong ke-14 hingga pagi hari panglong ke -15.
Bila pun ada tiga brata ini, dalam pandangan orang-orang suci, Jagra tetaplah menempati urutan paling utama. Sebab tanpa Jagra, dua brata lainnya tidak bisa dilakukan. Sampai pada titik ini, brata Siwaratri sesungguhnya adalah kepatuhan dan perjuangan melawan lupa. Siapa pun tengah dibelit lupa dipastikan dia berada dalam kondisi turu (tidur). Mereka yang senantisa tidur, atau tidak sadar, atau tan atutur. Dan bagi mereka yang tidak sadar, yang selalu tidur tidak mungkin terjadi kebangkitan kesadaran, alih-alih kebangkitan rohani. Kesucian [Siwa] tidak akan mendekat padanya.
Oleh : Wayan Westa
Kusa Agra,
Tilem Kapitu,
20-1- 2015



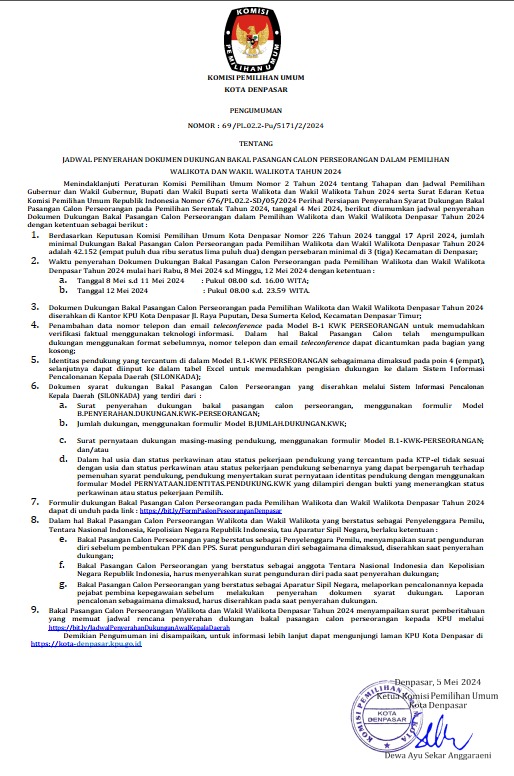









Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.