POLUSI VISUAL DI RUANG PUBLIK
PENGALAMAN visual masyarakat urban tidak melulu tersusun atas tumpukan gedung, pemukiman, dan arus kendaraan. Kota menyimpan detail visual yang melimpah. Mulai dari citraan komersial pada poster, billboard, dan banner berukuran raksasa, rambu-rambu lalu lintas, hingga coretan liar yang bertebaran di ruang publik.
Ruang publik yang dimaksud dengannya adalah tempat-tempat, biasanya dalam sebuah kota, yang dibuat dan disediakan untuk dipakai oleh masyarakat umum, tanpa membedakan jenis gender, umur, kelas sosial, agama sampai etnisitas. Dan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh publik pemakai tempat-tempat seperti itu pun beragam, mulai dari yang sekedar mencari tempat teduh dan rileks, tempat berolah raga sampai berpacaran.
Kampanye pemilihan gubernur Bali beberapa waktu yang lalu, tak lepas dari media-media peraga seperti spanduk, baliho, poster,sticker dan lain-lain. Di sepanjang perjalanan kita tak lepas melihat kesemrawutan pemasangan media peraga tersebut. Entah itu di tembok-tembok rumah, jembatan, taman, kendaraan-kendaraan umum, warung, pagar, pepohonan dan masih banyak lagi berbagai tempat yang dipasang dengan media peraga tersebut. Ruang publik akhir-akhir ini juga dipadati baliho atau banner dari oraganisasi masyarakat tertentu sebagai bentuk unjuk kekuatan (show of force).
Di sisi lain, lanskap kota diwarnai grafiti yang menyebar secara masif di banyak tempat, mulai dari tembok-tembok jalanan, pagar rumah, tembok sekolah, tiang listrik, toilet umum, jembatan, dan sebagainya. Kehadirannya tidak terbatas di kawasan tertentu. Grafiti pada umumnya bersifat anonymous, yang menggambari atau mencorat-coret dinding memakai cat tembok yang dikombinasikan dengan cat semprot dan spidol. Sementara seniman street art yang lain menuangkan ide dan gagasan mereka ke dalam bentuk wheat paste, yaitu gambar di atas kertas yang ditempel dengan menggunakan perekat dari tepung kanji (tapioka/aci) yang dididihkan. Wheat paste juga dikenal dengan nama Marxist glue, sebab di masa lampau kerap digunakan oleh organisasi beraliran kiri. Kini cara itu diadopsi untuk berbagai aksi seni rupa, termasuk dalam membuat karya street art, meskipun karyanya tak selalu bermuatan politis.
Teks atau dalam khasanah street art kerap digunakan untuk mewakili beragam ekspresi perasaan yang spontan, seperti marah (memaki, menyerapah), kaget, hingga olok-olok. Ekspresi yang diwujudkan secara vandal.Vandal adalah unsur penting dalam aktivitas street art. Coretan vandal yang nakal merupakan reaksi atas otoritas (sistem kekuasaan) yang melingkupi suatu ruang.
Sekarang kita mendapati “ruang publik” sebagai medan perang tanda. Ruang publik yang dipahami awam sebagai itu tempat-tempat yang dibuat dan disediakan oleh pemerintah untuk dipakai oleh masyarakat umum itu, menjadi arena berkompetisi produk komersial, pencitraan para birokrat, dan unjuk kuasa ormas atas wilayah tertentu. Di sisi lain,kritik dan rasa muak atas otoritas (system kekuasaan) yang diusung graffiti di tembok-tembok kota, membuat kita kehilangan orientasi: apakah kita hidup di Denpasar Timur atau di Bronx (NY).
Dalam mengelola”ruang publik”, para pemangku kebijakan (dan wacana) membawa kita ke konsep demokrasi, , sebuah kondisi kehidupan di mana masyarakat umum atau “publik” memegang peranan yang sangat penting. Konsep demokrasi mengisyaratkan bahwa kekuasaan politik yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat adalah kekuasaan yang memang benar-benar berasal dari masyarakat itu sendiri demi kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat memiliki kekuasaan mengawasi tepat-tidaknya kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh siapapun yang mereka pilih untuk melakukannya. Masyarakat umum atau publik memiliki kekuasaan politik paling tinggi dalam sebuah kondisi kehidupan yang disebut sebagai demokrasi. Partisipasi public dalam mengelola ruang publik
Kita mulai dari fenomena sederhana bahwa beberapa tembok di kota kita dicoreti, beberapa menarik perhatian kita, beberapa lagi menyebalkan dan biasa-biasa saja. Kita mencoba mencari alasan mengapa tembok-tembok itu dicoreti dengan harapan kita dapat merefleksikan diri dan memaknai sedikit banyak hal, seperti ekspresi individu dan seni misalnya, kondisi sosial dan budaya misalnya, atau mungkin ruang publik misalnya. Pertanyaannya sekarang adalah; mungkinkah?
Mungkinkah? Karena kita tidak sedang berada di New York circa 70-an, ketika kota itu disapu bencana ekonomi, hampir bankrut dan melewati sebuah proses transformasi sosial, politik dan budaya besar-besaran. Perkembangan teknologi dan perubahan infrastrukur yang dibarengi pula dengan pemotongan subsidi atas hampir semua pelayanan publik, tingginya angka kekerasan dan kriminalitas, rasisme akut, imigrasi besar-besaran plus penumpukan veteran perang Vietnam yang berhadapan dengan ketiadaan pekerjaan dan tempat tinggal yang cukup, semuanya meninggalkan para penghuni ghetto-ghetto di NY dalam kemiskinan sistematis dan dalam situasi ‘no-go’ dimana mereka yang diizinkan masuk adalah mereka yang tak diizinkan pula untuk keluar.
* Helmi Haska



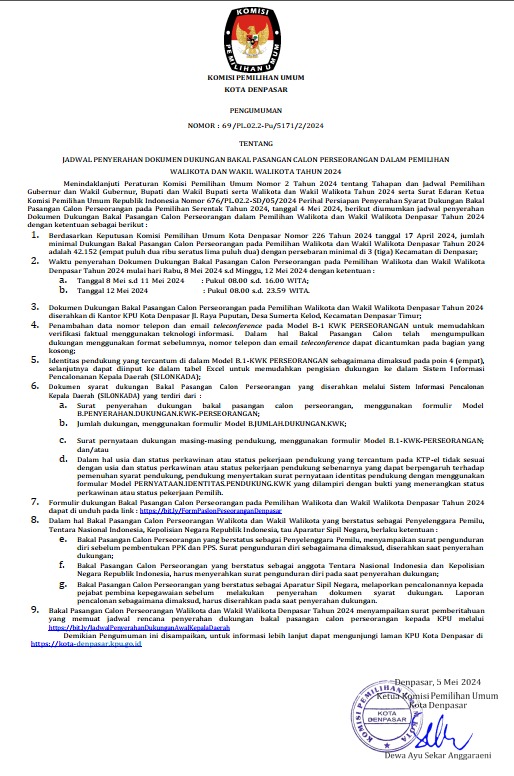









Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.