Politik Puri – Puri di Gianyar
PETA politik puri-puri di wilayah Kabupaten Gianyar tidak pernah terbagi dengan jelas secara ideologis. Kecenderungan afiliasi politik sebuah puri lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan sesaat dalam hubungannya dengan agenda-agenda politik puri pada suatu saat.
Dua buah puri besar di Gianyar yang mempunyai pengaruh politik cukup besar adalah Puri Ubud dan Puri Gianyar. Puri-puri lainnya, seperti puri Peliatan, Sukawati, Payangan, dll.nya tidak terlalu menonjol perannya dalam kehidupan politik. Puri Ubud dan Puri Gianyarlah yang lebih sering mewarnai perkembangan perpolitikan baik dalam skala lokal Gianyar, maupun skala regional Bali. Dalam proses pemilihan bupati Gianyar, misalnya, calon-calon yang tampil dipastikan setidaknya mencerminkan fragmentasi antara kandidat dari Puri Ubud dan Puri Gianyar. Rivalitas kedua puri dalam kancah politik memang sudah terbentuk sejak lama.
Kekuatan-kekuatan politik eksternal pun cenderung melakukan pendekatan kepada salah-satu puri tadi manakala hendak memulai ‘bermain’ politik di wilayah Gianyar. Ketika Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) mulai menancapkan pengaruhnya di bumi seni itu, misalnya, partai tersebut mendekati salah-satu tokoh puri Ubud yang baru saja gagal dalam proses pemilihan bupati Gianyar di pertengahan tahun 2003 lalu, yakni Cokorde Putra Arthadana Sukawati. Dengan menggandeng seorang tokoh puri kharismatik, sebuah partai akan merengkuh dua buah legitimasi sekaligus; sosial dan kultural.
Sesungguhnya aspirasi politik sebuah puri tak bisa dibaca tunggal, karena di dalamnya terdapat lagi faksi-faksi politik yang berbeda. Di kalangan puri Ubud, umpamanya, kaum bangsawannya sejak lama telah terbelah ke dalam dua aliran politik yang berbeda. Sebelum kegagalan Cokorde Putra Sukawati (Cok Ace) terpilih menjadi bupati Gianyar, puri Ubud terbelah ke dalam dua partai, yaitu PDIP (gerbong Cok Ace) dan Golkar (gerbong Cok Kertiyasa). Namun setelah kegagalan Cok Ace dalam pemilihan bupati, ia cenderung berafiliasi ke partai PIB. Suara puri bisa menyatu hanya ketika puri mempunyai ‘musuh bersama’ yang harus dihadapi bersama-sama. Begitu tujuan bersama tercapai, masing-masing faksi akan kembali ke dalam posisinya semula.
Fenomena yang menarik dicermati adalah strategi dan taktik yang dipilih pihak puri dalam menggalang dukungan politik dengan memanfaatkan dominasi-dominasi yang dimilikinya. Dominasi-dominasi tersebut dapat berupa ekonomi, budaya, sejarah, dan sosial. Puri Gianyar dalam memperkuat posisi politiknya cenderung memilih dengan memelihara dan memperkuat hubungan politik dengan pusat kekuasaan (Jakarta). Kedekatan tokoh-tokoh puri Gianyar dengan elite Jakarta, memang sudah terjalin sejak lama. Kedekatan tersebut berdampak terhadap ‘takdir politik’ yang diterima Puri Gianyar. Beberapa jabatan strategis bisa diraih oleh para tokoh puri Gianyar, seperti menteri, bupati. Hal ini jelas tak bisa dilepaskan dari kedekatan hubungan keluarga puri dengan pihak elite Jakarta (keluarga Presiden Megawati).
Berbeda dengan Puri Gianyar yang memilih penguatan posisi politik ke arah vertikal, Puri Ubud lebih terlihat melakukan perluasan pengaruh politik ke arah basis (grass roots) dengan memanfaatkan simbol-simbol budaya dan agama. Pengaruh politik tersebut ditanamkan pada desa-desa adat di wilayah inti (core region) Ubud maupun wilayah pinggiran (pheri-pheri) Ubud yang jauh, seperti daerah Payangan, Lodtunduh, dan Tegalalang. Di wilayah-wilayah pedesaan tersebut Puri Ubud melakukan semacam hegemoni ritus beragama yang lambat-laun berubah menjadi ketaatan dan kepatuhan desa-desa tersebut terhadap keinginan politik pihak keluarga puri.
Salah-satu strategi yang ditempuh, misalnya, dengan mengundang setiap sesuhunan (barong) di masing-masing desa klien tersebut dalam upacara-upacara yang digelar di Pura Gunung Lebah, Campuhan, Ubud (sebuah pura yang diemong oleh keluarga puri Ubud). Beberapa waktu sebelumnya, desa-desa tersebut diberikan bantuan perbaikan pembangunan atau rehab pura oleh puri Ubud, atau yang lebih spesifik, seorang Cokorde di puri yang mahir membuat tapel akan membuatkan tapel barong kepada sebuah pura di suatu desa pakraman tertentu. Sehingga ritus ngiring sasuhunan ke pura Gunung Lebah saban enam bulan tersebut terrekonstruksi menjadi sebuah proses balas-budi pihak desa pakraman kepada puri.
Pan Kari (bukan nama sebenarnya), ayah 5 orang anak berumur 67 tahun, warga sebuah desa adat di sekitar Ubud, membenarkan fenomena ini. Seingatnya, ritual ngiring sasuhunan ke Pura Gunung Lebah memang telah berlangsung sejak ia masih muda. Setiap piodalan di Pura Gunung Lebah, ia dan krama Singakerta lainnya akan berjalan kaki untuk ngiring sasuhunan ke pura tersebut. Demikian juga tatkala ada upacara di merajan agung milik Puri Ubud. “ Kami melakukannya karena merasa berhutang budi pada cokorde…,” ujar Pan Kari lirih.
Atau pada kasus lain, tatkala di merajan puri dilaksanakan sebuah prosesi upacara tertentu, para panjak puri yang terdiri dari krama desa yang jauh dari puri akan datang ngayah ke puri. Tentu keikutsertaan mereka ngayah karena sebelumnya sudah ada mobilisasi dari pihak bendesa adat desa pakraman setempat. Sebaliknya manakala desa yang bersangkutan melangsungkan upacara piodalan, pihak puri pun tak segan-segan datang ke pura desa pakraman tersebut. Selain bersembahyang tentu seraya menyerahkan dana punia.
Demikianlah, hubungan mutualisme saling menguntungkan memang telah terbina sejak lama antara puri dengan panjaknya. Lambat-laun akan tercipta ketergantungan desa-desa klien tersebut kepada puri Ubud sebagai patron.
Membangun basis dukungan massa melalui sarana simbol-simbol ritual bukan hal yang baru, memang. Hal tersebut juga telah dilakukan oleh raja-raja Bali di abad 19. Setidaknya fenomena ini jelas tersirat dalam penelitian Clifford Geertz dalam bukunya, Negara Teater, Kerajaan-kerajaan di Bali pada Abad 19 (terbitan tahun 1980). Menurutnya, Bali di abad 19 adalah sebuah negara teater yang di dalamnya raja-raja dan para pangeran adalah impresario-impresario, para pendeta sebagai sutradara, dan para petaninya sebagai aktor pendukung, penata panggung, dan penonton. Upacara pelebon yang megah, potong gigi, upacara di pura, dan caru, dengan mengerahkan ratusan bahkan ribuan orang dan harta yang banyak. Kesemuanya –saat itu—memang bukan untuk mencapai tujuan-tujuan politis tertentu, karena segala macam upacara itu sendiri adalah tujuan, di mana untuk semua itulah negara tersebut didirikan.
Saat itu, seremonialisme puri adalah daya gerak dari perpolitikan puri; dan ritual massa bukanlah alat untuk mendukung negara, tetapi negaralah sebagai alat untuk menggelar ritual masa tersebut.
Di titik inilah perbedaan peran upacara besar puri di era sekarang. Di abad ke 21 ini upacara megah dengan melibatkan ribuan massa lebih menempatkan upaya pamer kekuatan massa sebagai tujuan primer. Tujuan untuk mencapai kerahayuan bersama melorot menjadi tujuan skunder, bahkan tersier. Maka tak heran, bila upacara-upacara besar yang digelar oleh puri-puri saat ini sudah dipastikan akan dihadiri oleh pejabat-pejabat teras pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, propinsi, bahkan kalau memungkinkan akan mengundang pejabat pusat !
Tentu saja, ketika penyelenggaraan upacara besar menjadi pilihan sebuah puri untuk melakukan konsolidasi basis massa, maka pilihan tersebut harus diikuti oleh sumber daya ekonomi puri yang memadai. Sebab tidak sedikit jumlah uang, tenaga, dan waktu yang dihabiskan untuk sebuah upacara besar. Bisa dimengerti kemudian apabila pihak puri Ubud pada paruh dua dekade terakhir juga giat mengembangnkan bisnis keluarga mereka, terutama di sektor pariwisata. Beberapa hotel dan restoran besar di daerah Ubud, misalnya, memang dimiliki oleh figur-figur sentral puri Ubud.
Begitulah kehidupan politik puri di era modern. Di satu sisi ia telah kehilangan sumber-sumber dominasi masa lalunya. Namun, di sisi lain beberapa puri telah mulai menancapkan dominasi kekuasaannya dalam bidang-bidang yang lain. Bagaimanapun juga pengaruh puri sebagai sentrum dan patron kebudayaan dan politik di Bali tak bisa diabaikan begitu saja.
Sukma Arida



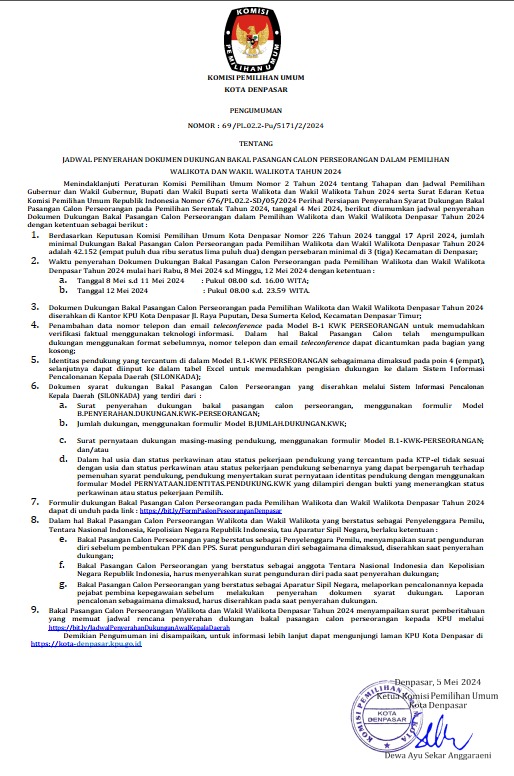









3 Komentar
“Selama abd ke-17 dan ke-18 Bali merupakan salah satu sumber budak yang paling penting di kepulauan Indonesia. Perdagangan budak tidak saja menghasilkan kekayaan bagi mereka yang berkuasa tetapi juga mempengaruhi hubungan antara raja dan orang kebanyakan karena para raja juag menjadi eksportir budak utama.” (Henk Schulte Nordholt, The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940, hal. 17).
strategi yg luar biasa,
jaya terus puri2 di bali