PEMBAHASAN RUU MASYARAKAT ADAT VS PETA KASUS DI BALI
PADA Zaman Hindia Belanda, Desa di Bali dan Jawa (seperti halnya Negari di Minangkabau, Kampung di Sumatra Utara, Marga dan Dusun di Palembang, dan lain-lain) adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara penuh menjalankan fungsi pemerintahan. Namun tatkala pada tahun 1979 diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, fungsi pemerintahan dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu, termasuk Desa di Bali, diambil alih oleh Desa (di wilayah pedesaan) atau Kelurahan (untuk perkotaan), sehingga dengan demikian praktis seluruh kesatuan masyarakat hukum adat itu mati-kecuali di Bali. Di Bali, Desa sebagai kesatuan hukum adat tetap hidup karena, meskipun tidak lagi melaksanakan fungsi pemerintahan, ia memiliki fungsi lain yang berkaitan dengan adat-istiadat dan agama (Hindu). Pada masa inilah mulai muncul istilah Desa Adat dan Desa Dinas untuk membedakan bahwa yang disebut terdahulu adalah kesatuan masyarakat hukum adat (fungsi pemerintahan) sedangkan yang disebut belakangan adalah bagain dari system pemerintahan (IDG.Palguna).
Dengan sejarah demikian, hingga saat ini masih saja ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan dari kedua desa tersebut. Pada awal pengalihan kewenangan dari Desa Adat kepada Desa Dinas, ada kewenangan tertentu yang tidak ikut dialihkan. Dengan kata lain, ada kewenangan atau elemen-elemen kewenangan tertentu yang tetap dipegang oleh Desa Adat (sekarang disebut Desa Pakraman). Tumpang tindih terjadi karena keberlakuan kewenangan dari dua Desa tersebut acapkali tertuju pada orang, wilayah, dan hal yang sama. Karenanya, dapat dimengerti kalau kerap terjadi gesekan dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud.
Perumusan tata hubungan yang jelas dan tegas antara Desa Adat (Desa Pakraman) dan Desa Dinas mustahil dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memahami keberadaan Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang amsih hidup. Keberadaan Desa Pakraman dan Hak-hak tradisional yang dimilikinya dilindungi oleh Konstitusi (UUD 1945). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 di atas berarti Konstitusi mengakui bahwa Desa Pakraman mempunyai kemampuan hukum (legal capacity) untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya di hadapan pengadilan. Kemampuan hukum untuk mempertahankan hak-hak tradisional itu bukan hanya terhadap perbuatan orang-orang perorangan tetapi juga terhadap perbuatan Negara. Selanjutnya, karena hak-hak tradisional itu secara tegas diakui oleh Konstitusi maka hak-hak itu berstatus sebagai hak Konstitusional sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran Konstitusional. Oleh karena itu, undang-undang pun tidak boleh melanggar hak-hak tradisional (yang telah diakui sebagai hak konstitusional) kesatuan masyarakat hukum adat tersebut.
KASUS-KASUS DALAM DINAMIKA HUBUNGAN DESA ADAT DENGAN DESA DINAS DI BALI
Sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (sudah dicabut), hingga kini dinamika hubungan desa Pakraman dan Desa Dinas di Bali masih saja mengalami “tumpang tindih/gesekan”. Misalnya dalam kewenangan mengatur wilayah/tanah, Lembaga Prekreditan Desa (LPD)/Lembaga keuangan milik desa adat, pola bantuan pemerintah, kependudukan, perijinan, pajak, retribusi, kepariwisataan, asset desa, desa adat yang berkonflik, kewenangan dan sebagainya. Namun tumpang tindih yang terjadi menyangkut atau tertuju pada orang, wilayah dan hal-hal yang sama dengan urusan yang berbeda, maka “gesekan” yang terjadi relative teredam bahkan cendrung mengarah ke “musyawarah”, untuk saling menguntungkan atau perdamaian.
Dalam perkembangan masyarakat Bali saat ini, dalam kedinasan (desa dinas) cendrung menuntut “azas ketegasan” hukum dan aturan dalam menjalankan kewenangannya. Sedangkan desa adat, dalam aturan desa adat (awig-awig) masih mengedepankan “azas kepatutan”. Walaupun keduanya sama-sama mengedepankan “azas kemanfaatan” yang sering bertujuan sama. Perubahaan UU dan peraturan lainnya yang begitu cepat dan beragam, pada prakteknya tidak selalu mudah diselaraskan dengan kebutuhan dan kemampuan desa adat. Disamping kesiapan SDM yang terbatas di tingkat desa adat, juga menyangkut tradisi/kearifan lokal dan teknis hukum lainnya.
PASKA PERDA DESA PAKRAMAN DAN TERBENTUKNYA MAJELIS DESA PAKRAMAN
Munculnya beragam kasus menyangkut tumpang tindih dalam pelaksanaan tata kelola hubungan desa adat dan desa dinas, maka atas desakan banyak pihak pemerintah daerah Bali pada tahun 2001 mencanangkan penyusunan Perda Desa Pakraman (Adat). Segenap komponen masyarakat di Bali menyepakati pentingnya mengevaluasi pola hubungan antara desa adat dan desa dinas, demi pembangunan Bali. Waktu itu muncul tiga pandangan utama yaitu : 1). Bubarkan desa dinas, selanjutnya menjadi sub ordinate dari desa adat. 2). Tetap mempertahankan desa dinas seperti semula karena antar desa dinas dan desa adat memiliki kewenangan yang berbeda. 3). Tetap mempertahankan desa dinas seperti semula, tetapi ada beberapa kewenangan desa dinas dikurangi atau dipangkas. Dari ketiga pilihan tersebut, akhirnya disepakati desa dinas tetap dipertahankan seperti semula.
Setelah melalaui perdebatan yang cukup alot akhirnya ditetapkanlah Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2001, dan mengalami perubahan menjadi Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2003. Berdasarkan mandat Perda Desa Pakraman maka dibentuklah Majelis Desa Pakraman (MDP), sebuah “lembaga payung Satu Langit” tanah Bali. MDP adalah lembaga representative desa adat di Bali. Satu satunya lembaga independen yang memiliki perda di Bali. Dalam kedinasan MDP bernaung dibawah dinas kebudayaan dan pariwisata.
Secara keseluruhan, tugas MDP mengkoordinasikan 1483 desa pakraman dan memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan (Majelis Alit), kabupatan (Majelis Mandaya) dan provinsi (Majelis Utama). Sayangnya hanya dengan modal Perda, MDP tidak bisa berbuat banyak. Aparatur MDP dan desa Pakaraman tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam teknis hukum Negara. Dan masalah pendanaan juga mengalami keterbatasan, padahal Bali menjadi “makmur” karena pariwisata budaya dan adat. Minimnya anggaran yang diperoleh MDP dari APBD, tidak lepas dari persoalan teknis hukum dalam system pembendaharaan kas negara. Misalnya aspek legalitas, NPWP, dll yang sering menjadi persyaratan pemanfataan kas negara. Sungguh sangat ironis, jika benar sebuah yayasan saja bisa dibantu 1 milyar dari APBD karena memiliki legalitas Negara. Sedangkan dana operasional MDP hanya dapat dana 500 juta per tahun.
Adanya Perda dan MDP, tidak secara otomatis persoalan hubungan tata kelola hubungan desa Pakaraman dan desa dinas (dalam hal ini Negara) menjadi tuntas. Masalah pun terus berkelanjutan dalam berbagai bidang. Sebagai contoh; dalam implementasi UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan asset desa adat menolak diberlakukan UU ini terhadap LPD. Namun karena adanya istilah “Perkreditan” yang menurut UU perbangkan (BI) merupakan peristilahan perbankan, maka semua lembaga keuangan mikro (termasuk milik desa adat) harus menyesuaikan. Ada usulan untuk merevisi Perda Desa Pakraman dan Perda Lembaga Perkreditan Desa, entah kapan?
Sementara dalam hal kewilayahan/tata ruang, konflik yang muncul dan cukup alot adalah implementasi RTRWP Bali No. 16 Th 2009. Oleh Pemerintah Provinsi (Gubernur) RTRWP ini dibuat untuk memberi perlindungan terhadap wilayah adat. Namun malah ditentang oleh bupati dengan berbagai kepentingan. Ada kesan para Bupati ngotot menentang RTRWP Bali No. 16 Th 2009 karena adanya kepentingan pragmatis, dan berlindung dibalik kewenangan otonomi daerah. Istilahnya “Mau arif atau mau duit?” Kalaupun toh RTRWP salah, semestinya tetap bisa dikoreksi dalam “memperteguh” prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan nilai-nilai luhur adat dan desa Pakraman.
Kasus lainnya menyangkut pajak. Misalnya tanah atau asset desa adat banyak yang tidak menghasilkan secara ekonomi (pendapatan/Uang), tapi memiliki nilai budaya dan seni yang mendukung pariwisata. Belum lagi situs-situs adat lainnya seperti Subak. Banyak terjadi masyarakat adat/subak hanya dapat “uang parkir” saja, sedangkan akumulasi pendapatan dari sector pariwisata Bali yang jumlahnya Triliunan tidak dikembalikan kepada perlindungan dan penghormatan nilai-nilai adat.
Dalam hal pembangunan infrastruktur (fasilitas umum) yang dibangun diatas tanah adat, sering kali menjadi “bom waktu”. Bahkan belakangan banyak pihak juga sepakat kalau dana-dana bantuan tidak diberikan langsung ke desa adat. Karena lemahnya SDM dan pengetahuan teknis hukum di tingkat desa adat sering kali menimbulkan persoalan baru. Ditenggarai timbulnya “konflik bernuansa adat” belakangan ini karena adanya “aroma” perebutan dana “bantuan” / dana pembangunan.
Belakangan ini yang tidak kalah peliknya adalah menyangkut “desa adat yang berkonflik” dan atau “kasus krimininal murni yang diadatkan”. Yang menarik, baru saja dan masih berlangsung, konflik antar dua desa adat di Kab. Klungkung saat ini “berbuah” perseteruan antara Gubernur Bali dengan Media Bali Post (Kasus ini bahkan masuk ke ranah hukum/pengadilan karena masalah pemberitaan yang keliru).
Ternyata banyak sekali permasalahan yang harus diurai. Namun patut disyukuri, belum selarasnya tata hubungan desa pakraman dan desa dinas di Bali bukan dilandasi oleh niatan untuk saling melemahkan baik oleh desa pakraman maupun desa dinas. Bahkan keduanya adalah “korban” keterbelenguan aturan Negara yang multi tafsir. Dan tentu jika nanti disahkan dan diberlakukannya RUU Desa dan RUU Masyarakat Adat, problema baru pasti akan terjadi lagi.
Masih ada puluhan kasus yang belum terpecahkan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah hal ini akan dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang berwenang/negara? Dan bagaimana gerakan masyarakat adat di nusantara (Termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN) mengetahui dan memahaminya sehingga arah gerakan masyarakat adat nusantara menjadi jelas mulai dari mana, dimana, dan kemana? Benarkah eksistensi masyarakat adat bisa tumbuh dan berkembang karena pemberian pengakuan oleh Negara? Bagaimana pula dengan komunitas adat lain di belahan bumi nusantara, yang baru saja bergeliat? Benarkah UU masyarakat adat adalah “kabar gembira” bagi masyarakat adat nusantara? Dan seterusnya.!
Dalam Peta Kasus di Bali, mengakarnya kewajiban dan aktivitas adat sehari-hari, cukup memberi jaminan bahwa perubahan akan berjalan relative damai. “Karena visi masyarakat adat Bali hasil rumusan terbaru Majelis Desa Pakaraman Bali adalah; Bali Shanti (Bali Damai). Melalui kebersamaan, kesepakatan menuju kedamaian”. Faktor yang menguntungkan lainnya adalah; dari segi sejarah, aliansi budaya dan tradisi, satu Pulau Bali adalah seutuhnya merupakan wilayah/tanah desa Pakraman/adat dan sekaligus juga merupakan wilayah tanah desa dinas. Kelemahan SDM di tingkat desa adat juga cukup terbantu dengan adanya Jurusan Hukum Adat di Universitas Udayana, yang cukup memberikan andil dalam perumusan dan konsultasi legal drafting bagi Komunitas Adat/Pakraman.
Semoga semua yang terlibat dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR RRI, tetap memiliki keteguhan hati untuk melakukan perubahan menuju masyarakat/desa adat dan dinas yang lebih mandiri, bermanfaat, dan bermartabat (**).
Made Nurbawa
(Ketua BPH AMAN BALI)



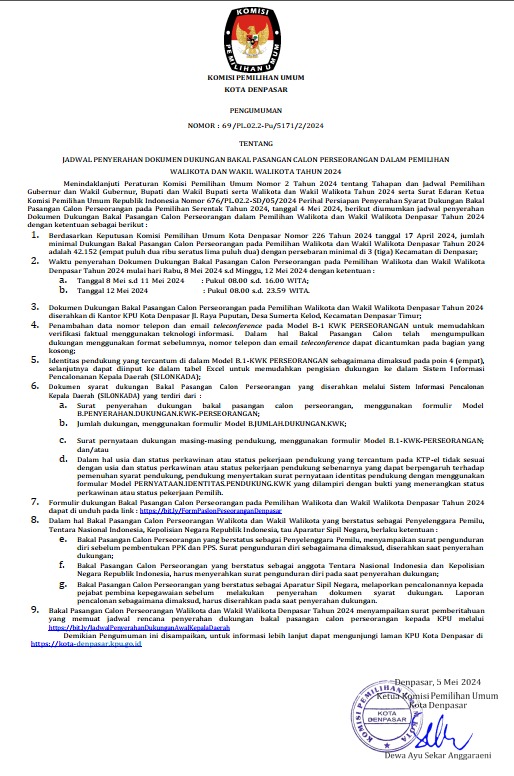









4 Komentar
koreksi: Majelis Desa Pakraman tidak berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Ketut bali.Terimakasih atas koreksinya.
salam,
kalau ditelisik filosofi tentang hubungan antara hukum positif dengan keberadaan desa pakraman dalam hal ini sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) makaa sebenarnya bagi desa pakraman yang diperlukan adalah adanya pengakuan dari negara, yang pengakuan tersebut adalah berbentuk peraturan perundang-undangan yang mana di daerah disebut dengan PERDA. dalam perkembangannya didalam perda tersebut kemudian tidak hanya diatur tentang pengakuan desa pakraman tetapi juga diatur tentang berbagai hal seperti susunan, syarat desa pakraman, LPD dan MDP yang notabenenya bersifat otonom…. idealnya yang mengatur tentang hal-hal tersebut adalah DESA Pakraman itu sendiri bukan diatur oleh PERDA.
mengkaji tentang PERDA yang sebenarnya berada di bawah PP, UU, TAP MPR, UUD, sebagaimana dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan maka desa pakraman harus tunduk pada peraturan diatas perda tersebut, maka akan menjadi masalah kedepannya dalam hal otonomi desa yang dimiliki desa…. apa yang terjadi kemudian…. pemekaran harus dicatatkan padahal dalam hal pengakuan desa pakraman tidak perlu dicatatkan, awig-awig harus tertulis, menjadi desa pakraman harus memiliki kahyangan tiga (padahal secara de facto beberapa desa pakraman ada yang tidak memiliki salah satu dari kahyangan tiga, desa pakraman kemudian memperjelas identitas seperti jumlah krama, batas desa dll, padahal tanapa harus demikian mereka sudah diakui sebagai desa pakraman…. APA dan bagaimana bisa menjadi demikian tiada lain karena adanya motifasi memajukan Desa yang hendak dicapai yang dilakukan dengan SUMBANGAN pemerintah yang begitu banyaknya… dan Sumbangan tersebut itupun lebih banyak ke bangunan fisik…. jadi Perda ini seharusnya di revisi cukup di pengakuan saja dan masalah diinternalnya biarkan desa pakraman yang menentukan… suksma
Pak Made sekarang kan sudah terpenuhi permintaan Bpk, tentang pengakuan/kepastian hukum Desa Adat oleh Bpk2 DPR di Senayan. Astungkara Pak Made, semoga orang -orang tamak,malas agar tersingkir dari komunitas warga adat. Seperti contoh rencana pembuatan Setra oleh suatu Suka-duka “XXXX” dari suatu Desa (di pusat kota Kabupaten Bgl), yang akhirnya di tolak secara Tegas oleh Pemerintah dan Prajuru2 Adat. Astungkara.