Menggoreng Mimpi Soekarno
Di lubang galian masa lampau,
berserakan fosil Goak ,
bertaburkan kulit telor bebek,
Goakkah sekumpulan masa lampau,
Goak memang si burung Gagak,
berbulu hitam,
berbadan besar,
bersuara keras,
Soekarno Sang Presiden
yakinkan aku, tidak,
masa lampau bukan sekumpulan Gagak
masa lampau sekumpulan Merpati,
penuh senyum perdamaian,
indah gilang-gemilang,
andai benar adanya,
pantaskah sang pewahyu rakyat berkata dalam sepi,
mengurung diri di tengah kemegahan busana,
sejarahkah yang berjalan tak lurus,
terputus atau berkelok haluan,
sampai sang pewahyu rakyat hilang arah,
hanya menoleh ke masa lampau,
tak mau mengganti kulit dikalahkan seekor ular,
tampaknya sang pewahyu rakyat sedang berjalan di atas awan,
tiada bayang-bayang Merpati melintas di pelupuk mata,
lautan tampak semakin menguning,
danau menghitam,
sawah-sawah memerah,
sekumpulan Gagak berseliweran,
gilang gemilang mengepak sayap,
di atap rumah membawa tanda bahaya,
mengubah parit jadi bungalow,
menggundul hutan,
menelan pasir kerikil mencipta kubang bermandi lumpur,
diiringi suara lirih bertalu,
dug, dug. gir, dug, dug, gir, dug, dug, gir,
luwune madugdug, punyan nyuhe ligir,
pedagang balon, bakso ayam, martabak, dan telor puyuh rebus,
berkeliaran menghapal dewasaning ayu,
itukah masa kini yang penuh perjuangan,
ataukah masa apa ane ada jeg juang
itulah kisah negeri burung Gagak,
akankah generasi serba gamang,
melahirkan masa depan cemerlang,
Soekarno bermimpi atau kita salah menggali,
andai sejarah berjalan lurus,
burung-burung Gagak tak akan melahirkan Merpati,
kecuali dengan memenggal sejarah,
mencipta agama baru disebut Revolusi Moralitas,
enak didengar,
indah dilihat,
sulit dilaksanakan,
Revolusi Moralitas mesti didahuli Revolusi Sistem Moralitas,
siapa berani menyentuh,
di tengah-tengah semarak komudifikasi moralitas,
menyentuh apalagi mengubah engkau kutangkap,
kumusuhi, kusisihkan, dan kujewer,
tidak kusertakan dalam kuasa,
perdagangan sistem moralitas mengantar kenikmatan duniawi,
bagai kopi tubruk di pagi hari,
menyapu pening dan kernyit dahi,
merasuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler,
mengubah sistem moralitas,
bagai membelah laut,
menampar angin,
memanah badai,
meluruskan ekor anjing,
sistem moralitas dibelit relasi kuasa tanpa pangkal,
menyelingkuhi selir-selir kehidupan,
bagai Hyang Ilahi ada di mana-mana,
tidak terikat ruang waktu,
Capra sudah mengingatkan,
dunia dilanda krisis multidimensional,
tak ada solusi kecuali merubah sistem,
sama dengan memerciki diri tirta pangentas
sebagai hiburan,
silakan nyanyi bersama,
Goak Maling Nak Luh,
Suudang ngoreng taluh ne misi lengkong.
Nyoman Wijaya, Singaraja, 1 Mei 2010
Pengantar
Ada apa dengan moralitas negeri ini, sehingga diperlukan revolusi moralitas? Apa hubungan antara revolusi moralitas dengan sempalan pidato Bung Karno, “Jadilah pewahyu rakyat…Fakultas Udayana harus menggali masa lampau kita yang gilang gemilang, masa kini yang penuh perjuangan dan masa datang yang cemerlang.” Apakah kedua variabel ini semacam kritikan, karena biarpun usia sudah mencapai lebih dari setengah abad, namun Faksas belum mampu membangun moralitas anak negeri, sehingga harus segera dilakukan revolusi moralitas. Jika demikian adanya, dari mana revolusi moralitas harus dimulai, di dalam atau di luar kampus? Jika dari dalam, lalu, ada apa dengan moralitas Faksas, darimana dan bagaimana cara memulai revolusi moralitas Faksas, sebab tidak akan ada yang mengakui dan menyatakan dirinya mengalami pendangkalan moralitas. Jika dari luar kampus, apakah Faksas sudah dan akan mampu melaksanakannya?
Mungkin memang ada kaitan antara revolusi moralitas dengan sempalan pidato Bung Karno yang kini sudah berumur 52 tahun. Usia yang cukup tua, namun tidak ada tanda-tanda hasil galian Faksas mampu memperbaiki moralitas anak negeri. Negeri ini tetap dihuni oleh para majikan dan kuli, yang kepentingannya dihubungkan oleh para spekulen. Spekulen adalah orang-orang yang mencari keuntungan besar dengan cara spekulasi dan kolaborasi. Segala sesuatu bisa mereka spekulasikan dan kolaborasikan. Saat mereka beroperasi di sektor pertanahan untuk menyenangkan para majikan yang berpaham kapitalis klasik, maka fungsi lahan hutan dan sawah semakin jauh bergeser, melebihi alih fungsi lahan di zaman kolonial dan Orde Lama. Saat berada di lembaga pengadilan, mereka menjadi Markus, Makelar Kasus. Bagaimana jadinya jika spekulen bermain di kampus? Di mana pun para spekulen bermain, di situ ada kehancuran. Saat bermain di dunia spiritual, para spekulen melahirkan praktek-prektek keagamaan yang lebih mengutamakan ritual daripada hakekat agama. Dulu di zaman enteg gumi (kerajaan), ketika perpaduan trilogikuasa pengadilan-bhayangkara-penjara sangat dominan, semua tubuh mendisiplinkan diri supaya selaras dengan wacana kekuasaan.[1] Akan tetapi ketika terjadi transformasi kekuasaan, orang-orang yang tidak puas atau yang menjadi korban praktek-praktek komuditifikasi spritualitas, ramai-ramai minggir dari masa lampaunya melalui konversi agama.[2]
Dalam kasus itu, siapakah yang salah, apakah Bung Karno yang asal-asalan menerapkan teorinya di Bali ataukah civitas akademika Faksas yang tidak mampu menggali dan memaknai masa lampau secara baik dan benar. Apabila teori pendidikan berjalan lurus, maka sejarah Bali masa kini seharusnya sudah memasuki masa pencerahan, karena setelah program pendidikan berhasil mengubah individu-individu, maka selanjutnya individu-individu yang telah berubah itu akan mengubah lingkungan sekitarnya.[3] Kenyataannya, masa pencerahan tidak penah terbentuk, padahal sudah beratus-ratus teks masa lampau digali, diterjemahkan, dan dipelajari menyerupai situasi masa Renaissance di Eropa. Pencerahan hanya terlihat pada mata dan hidung yang semakin cerah dan mengembang setelah melihat uang. Jadi, jumlah para spekulen yang matanya tercerahkan oleh sinar biru uang semakin banyak. Uang dan komoditas, sekarang ini bahkan mulai menggantikan hubungan antar manusia dan menggantikan konsep pawongan dalam trihitakarana menjadi pauangan. Uang (jinah) tidak saja membedakan-bedakan manusia, tetapi juga menghilangkan esensi kemanusiaan mereka.[4]
Faksas seperti tidak berdaya menghadapi fenomena itu, yang jika dicermati secara historis sudah tampak dari sejak awal pendiriannya. Tanpa mengecilkan arti keberhasilan individu-individunya, secara kelembagan Faksas tampak gagal mewujudkan impian Bung Karno sebagai Pewahyu Rakyat. Jurusan Purbakala hanya mampu bermain di darat melanjutkan penggalian para orientalis, tidak tergugah menjawab tantangan masa depan Arkeologi Kelautan. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia lebih berhasil melahirkan insan-insan di media cetak, antara lain menjadi editor ejaan, cerpenis, dan novelis, tanpa memikirkan pengembangan ilmu lain seperti Cinematografi dan Multimedia. Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris sangat menonjol dalam pembentukan pengusaha dan kuli di sektor indutri kepariwisataan, antara travel biro dan pemandu wisata. Jurusan Antropologi menonjol dalam membantu mengabsahkan politik kebudayaan pemerintah, yang dikemudian hari terbukti banyak kelirunya, misalnya dukungan terhadap konsep pariwisata budaya tahun 1970-an. Jurusan sejarah lebih berhasil menjadi penceramah dalam perayaan hari-hari bersejarah daripada menghasilkan karya-karya sejarah spektakuler sesuai dengan perkembangan metodologi sejarah modern. Jurusan Sastra Daerah, asyik dengan teks-teks terjemahan, menjadi konsultan dalam proses sansekertaisasi istilah-itilah pembangunan, dengan hanya sedikit memperhitungkan konteks sosial sesuai dengan kemajuan teori-teori ilmu sosial modern. Secara umum, karena faktor ekonomi dan alasan-alasan yang sangat pribadi, banyak pribadi yang tidak berjalan pada garis linier keilmuan, sehingga kaki mereka berada pada dua atau bahkan tiga titik keilmuan, yang semoga saja di kemudian hari tidak sampai mengganggu penilaian dalam proses akreditasi.
Demikianlah, gambaran umum perkembangan keilmuan di balik setengah abad usia Faksas, namun studi ini tidak dimaksudkan untuk membicarakan kelebihan maupun kekurangan keilmuan di Faksas. Permasalahan yang dibahas dalam paper ini lebih difokuskan pada hubungan antara ketidakberdayaan Faksas dalam mengolah sumber moralitas, terutama cerita rakyat dengan adanya kecenderungan umat Hindu di Bali tidak bersikap kritis terhadap agamanya. Apakah masa lampau tidak memiliki teks yang mengajarkan umat manusia bersikap kritis terhadap agama Hindu atau Faksas yang tidak tahu lokasinya, sehingga masa kini menjadi ibarat sekumpulan burung Gagak. Ketidakberdayaaan Faksas mengolah sumber moralitas, biarpun bukan menjadi penyebab utama, namun tetap merupakan bagian dari sebab-sebab yang mengakibatkan sebagian besar warga masyarakat Hindu di Bali di era Globalisasi ini masih lebih mengutamakan ritual daripada hakekat agama, yang akhirnya meningkatkan kasus konversi agama. Rumusan masalah itu dijabarkan melalui pertanyaan penelitian, yakni bagaimana model-model Faksas menggali dan memaknai cerita rakyat sebagai sumber moralitas dan hal-hal apa yang harus dibenahi dalam pemaknaan sumber moralitas itu?
Mengingat terbatasnya ruang dan waktu, jawaban pertanyaan penelitian ini dicari hanya pada dua buah cerita rakyat, yaitu Pan Botoh Lara yang digali dan dikupas oleh Profesor I Gusti Ngurah Bagus dan Mayadenawa oleh Profesor I Nyoman Weda Kusuma. Biarpun kedua Guru Besar ini tidak pantas disebut sebagai refresentasi Faksas, namun gaya dan cara mereka mengupas cerita rakyat dapat disebut sebagai model Faksas, karena keduanya tentu sudah menurunkan gaya analisis mereka kepada anak didik masing-masing, baik di S-1, S-2, maupun S-3.
Kisah Pan Botoh Lara
Pada suatu kesempatan, Profesor I Gusti Ngurah Bagus menggali cerita rakyat dari Desa Tenganan berjudul “Pan Botoh Lara.”[5] Dongeng ini berkisah tentang seorang laki-laki Pan Botoh Lara dengan burung Curik kepunyaannya. Burung kesayangannya itu terpaksa mau dibunuh oleh Pan Botoh Lara karena telah membocorkan rahasianya mencuri dan menyembelih seekor sapi milik Pan Saplar. Pan Botoh Lara akhirnya membatalkan niat itu, setelah Burung Curik berjanji akan menikahkan dirinya dengan anak gadis Pan Blandang. Burung Curik terbang ke rumah Pan Blandang, bersembunyi di sanggah. Dia bersuara bagai suara dewa leluhur, memerintahkan keluarga Pan Blandang mendekat sambil membawa sesajen. Burung Curik mengutarakan keinginannya untuk meminta anak gadis Pan Blandang, Ni Ketut Kawi dikawinkan dengan Pan Botoh Lara. Jika menolak dia akan dikutuk terkena penyakit lepra, tidak lagi memiliki keturunan, dan satu persatu keluarganya akan mati. Pan Blandang menyangka yang berbicara betul-betul adalah dewa leluhurnya. Karena itu dia menyanggupi semua permintaan Burung Curik. Keesokan harinya Pan Blandang anak gadisnya ke rumah Pan Botoh Lara untuk dinikahkan.
Sebulan berlalu, rahasia perkawinan itu terbongkar. Kisahnya bermula ketika Burung Curik tidak kuat menahan lapar dan haus akibat dari kelupaan Pan Botoh Lara menyediakan makanan untuknya. Dengan berbagai upaya dia mampu ke luar dari sangkarnya. Begitu berada di alam bebas, Burung Curik lalu memakan beras yang akan dimasak oleh Ni Kawi. Melihat hal itu Ni Kawi marah, lalu melempari Burung Curik, tetapi tidak mengenai sasaran. Burung Curik dengan sigap menghindar, lalu hinggap di tempat penyimpanan air. Ni Kawi kembali melemparinya dan sekali lagi tidak mengenai sasaran. Justru tempat air itu, pecah, hancur berantakan terkena lemparannya. Ni Kawi semakin marah. Burung Curik meminta agar Ni Kawi menghapus kemarahannya, lalu membongkar rahasia pernikahannya dengan Pan Botoh Lara. Ni Kawi pun bersedih, lalu minggat dari rumah suaminya. Mendengar penuturan anaknya, Pan Blandang mencoba menenangkan diri sambil mencari akal. Dia menyuruh Ni Kawi bersikap sewajarnya, seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun.
Pan Blandang mengatur strategi balas dendam. Ia meminjam Burung Curik itu dengan alasan tertarik dengan suaranya, padahal niat sebenarnya untuk dibunuh. Pan Botoh Lara mengizinkannya. Begitu sampai di rumahnya, Pan Blandang menginjak-injak sangkar burung itu sampai rusak. Tidak puas dengan itu, dia mencabuti bulu-bulu burung itu. Di saat Pan Blandang lengah, si burung curik berhasil melepaskan diri dan bersembunyi sampai sembuh. Burung Curik pun menyusun rencana balas dendam. Kini dia bersembunyi di meru Pura Puseh, milik desa tempat tinggal Pan Blandang. Saat itu warga desa sedang rapat. Kesempatan ini digunakan oleh si burung Curik sebaik mungkin. Dia kembali berpura-pura sebagai dewa di pura itu. Suara yang menggelegar mengejutkan warga desa. Kepada warga desa dia mengatakan desa ini sudah tercemar, yang diakibatkan oleh ulah Pan Blandang. Warga desa bertanya mencari jalan keluarnya. Si burung Curik memerintahkan menangkap Pan Blandang, memarut kepalanya dan membubuhinya dengan secangkop tumbukan bumbu dapur. Warga desa melaksanakan perintah itu. Setelah upacara bersih desa selesai, Pan Blandang dilepas, diperbolehkan pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar suara si burung Curik itu, yang menanyakan mana yang lebih menyakitkan, apakah terparut atau tercabut. Pan Blandang tidak memberikan jawaban. Dia terus melangkah menuju rumahnya, tanpa menoleh si burung Curik.
Profesor I Gusti Ngurah Bagus menggali makna cerita itu dengan cara mengkaitkannya pada sistem kekerabatan. Menurutnya, ada dua ikatan kekerabatan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui dongeng itu, pertama, resiko yang akan dihadapi oleh seseorang jika tidak mengikuti petunjuk dari para dewa. Orang yang tidak mengikuti petunjuk para dewa akan memperoleh sanksi. Dalam cerita ini sanksi itu dinyatakan berupa sakit gede (sakit lepra). Orang yang terkena penyakit lepra harus disingkirkan dari masyarakat. Kedua, makna keturunan dalam sistem kekerabatan orang Bali. Seorang anak mempunyai arti yang sangat penting. Tidak mempunyai anak (camput) akan membuat sanggah tidak terpelihara semestinya. Pemeliharaan ini tidak semata-mata secara material, membersihkannya dari berbagai kotoran atau memperbaiki kerusakan bangunannya, tetapi juga menyelenggarakan upacara penghormatan kepada leluhur pada hari-hari tertentu. Lalai dalam hal ini akan menimbulkan petaka dan diyakini orang-orang yang tidak mempunyai keturunan pada akhirnya tidak akan masuk ke sorga.
Profesor I Gusti Ngurah Bagus juga menjelaskan, dongeng itu memberikan gambaran mengenai ikatan kemasyarakatan orang Bali. Dalam sistem kemasyarakatannya, orang Bali terikat oleh pola relasi dengan anggota masyarakat desanya, misalnya wajib menjaga kesucian desa agar terhindar dari berbagai kecemaran (leteh). Sebuah desa dianggap tercemar jika di dalam lingkungan atau wilayahnya terjadi berbagai petaka seperti pembunuhan, bunuh diri, perselingkuhan, penyimpangan seksual, perkosaan, dan tindakan-tindakan amoral lainnya. Dalam upaya untuk membersihkan kembali desa yang telah tercemar, anggota masyarakat desa wajib melakukan upacara ruwatan. Jenis upacara seperti ini misalnya lukat, pecaruan, taur, labuh gentuh, dan sebagainya. Upacara ini terkait pula dengan pola relasi orang Bali lainnya, yakni kewajiban menghormati leluhur desa yang dipuja di Pura Puseh, sebuah pura yang paling disucikan oleh masyarakat desa. Oleh karena kesuciannya, warga masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan menempatkan pura ini di kaja, arah ke gunung. Mereka menjaga kesucian pura ini dengan melakukan berbagai upacara.
Cerita Mayadenawa
Menurut I Nyoman Weda Kusuma, teks Mayadenawa diperkirakan ditulis oleh Danghyang Nirartha pada akhir abad 15, masa pemerintahan Raja Gelgel Dalem Waturenggong (1460-1550). Teks ini menceritakan kisah Mayadenawa, putri Dewi Danu dan Resi Kasyapa. Melalui pertapaan yang ketat, Mayadenawa berhasil memperoleh kesaktian dari Mahadewa. Dengan kesaktiannya itu, Mayadenawa dan pengikutnya ingin menghancurkan surga, merusak tempat-tempat pertapaan, melarang warga masyarakat melaksanakan upacara (yadya), dan mencela ajaran agama. Dewa Iswara kemudian menyuruh Dewa Indra membunuh Mayadenawa. Dewa Indra melaksanakan suruhan itu. Ia pun menyuruh Bhagawan Wrehaspati menyelidiki keadaan di Bali. Berdasarkan hasil penyelidikan itu, Dewa Indra bersama dengan para pengikutnya menyerang Mayadenawa. Mayadenawa melawan musuhnya dengan gagah berani. Biarpun memiliki kesaktian yang luar biasa, namun akhirnya Dewa Indra dan pasukannya berhasil menaklukkan Mayadenawa.[6]
Lebih lanjut I Nyoman Weda Kusuma menjelaskan, setelah usai melaksanakan pesta kemenangan yang gegap gempita, Dewa Indra menyuruh roh Mayadenawa dan roh Nagani yang sedang bertapa supaya menjelma menjadi manusia untuk menegakkan kembali tata kehidupan di Bali sesuai dengan norma-norma kebaikan. Akan tetapi kedua roh itu menolak karena menganggap hidup sebagai manusia merupakan penderitaan secara halus. Mereka meminta supaya dibiarkan tinggal di neraka untuk bertapa supaya bisa menjadi apsara-apsari. Kehendak Dewa Indra tak bisa dibantah. Keduanya dimasukkan ke dalam seludung kelapa dan diletakkan di suatu tempat pemujaan. Pemangku yang berkarya di pura itu melihat seludung kelapa sebagai benda aneh, lalu membuangnya, namun keesokkan harinya benda itu kembali muncul ditempat semula. Pembuangan dan pemunculan itu berlangsung sampai beberapa kali, sampai akhirnya seludung kelapa itu berubah wujud menjadi sepasang anak laki dan perempan. Kepada pamangku, mereka menjelaskan identitasnya dalam kehidupan sebelumnya dan tujuannya diutus ke dunia oleh Dewa Indra. Anak yang laki menjelaskan dirinya sebagai Mayadenawa, sedangkan yang perempuan sebagai Naga Ratna Malini, anak raja naga Anantabhoga dan Wabyara. Mereka mengaku diperintahkan oleh Dewa Indra supaya lahir kembali k dunia untuk berbuat kebaikan demi umat manusia. Setelah dewasa mereka menikah dan melahirkan anak kembar buncing (laki dan perempuan). Setelah anaknya dewasa, mereka moksa. Tapohalang adalah generasi mereka yang ketujuh, yang akhirnya moksa juga. Tapohalang mempunyai 12 orang putra, namun hanya 11 yang moksa. Anak yang tidak moksa itu bernama Tokawa, yang tidak bisa moksa karena menikah dengan manusia biasa. Tokawa kemudian menjadi raja. Ia memiliki seorang anak bernama Makabika, yang juga tidak moksa.
Dalam analisisnya, Profesor I Nyoman Weda Kusuma menyatakan teks Mayadenawa mengandung ajaran-ajaran kepercayaan yang bersifat Siwaistis. Pada saat penulisan teks Mayadenawa (akhir abad ke-15), yang berkembang adalah aliran Saiwasiddhanta. Agama Siwa menurut Profesor Weda Kusuma mengenal tiga kerangka dasar yaitu, tattwa (filsafat), susila (etika), dan upacara (yadnya). Ketiga konsep itu tidak dapat berdiri sendiri. Dalam ajaran Saiwasiddhanta, Siwa adalah Tuhan, namun karena sifatnya yang mahakuasa, maka Tuhan diberi berbagai nama sesuai dengan sifat, fungsi, dan aktivitasnya. Selanjutnya, Weda Kusuma menyampaikan konsep-konsep keagamaan yang melekat dalam teks Mayadenawa. Guru Besar Faksas itu pun sampai pada tesis bahwa mitologi teks Mayadenawa dimaksudkan untuk mengukuhkan pelaksanaan ajaran agama Siwa di Bali. Siapapun yang melanggar atau melalangnya, menurut Profesor Weda Kusuma akan mendapat malapetaka seperti dialami Mayadenawa.
Analisis Lintas Ilmu
Analisis yang disampaikan oleh kedua Guru Besar Faksas dari dua generasi yang berbeda itu boleh-boleh saja dan mungkin harus dianggap benar sesuai dengan sudut pandang ilmu masing-masing. Akan tetapi sebagai satu kesatuan, dengan mengatasnamakan Faksas, masih tetap diperlukan penafsiran atau pemaknaan dengan beraneka macam cara untuk menghasilkan pembacaan yang beragam, tidak selalu seragam, sekalipun hasilnya bertentangan dengan yang dihasilkan oleh kedua Guru Besar itu maupun analis-analis lainnya. Sama dengan analisis terhadap Tosning Dadap Tosning Presi, kedua dongeng itu (Pan Botoh Lara dan Mayadenawa) juga bisa disebut sebagai sebuah perlawanan sehari-hari kelompok terintas terhadap hegemoni sekte Saiwasiddhanta [7]
Dalam kasus Pan Botoh Lara, cerita itu bisa disebut sebagai upaya untuk menggoyang sistem kepercayaan Hindu Saiwasiddhanta yang disimbolkan dengan konsep palinggih sanggah, dewa, meru,[8] dan pura puseh. Konsep itu jelas bukan kepunyaan penduduk asli Desa Tenganan, karena pada dasarnya mereka bukan pengikut kebudayaan Hindu Saiwasiddhanta. Sistem kepercayaan Hindu menyebar ke Tenganan melalui relasi-relasi kekuasaan kerajaan-kerajaan Bali. Pemahaman ini tampaknya sesuai dengan yang diterangkan oleh Profesor I Gusti Ngurah Bagus, bahwa cerita itu berkembang jauh dari pusat kerajaan yakni di Desa Tenganan Pegringsingan, salah satu desa kuno di Bali. Kisah “Pan Botoh Lara” ada juga dalam bentuk geguritan (puisi) ditemukan di Desa Bugbug, yang letaknya tidak jauh dari Desa Tenganan. Dari segi bahasa yang digunakan, Profesor I Gusti Ngurah Bagus menarik kesimpulan, cerita ini tidak asli dari desa Tenganan Pegringsingan melainkan campuran dari variasi Tenganan dan Bali Umum. Hal ini menurut Profesor I Gusti Ngurah Bagus dapat dilihat dari pemakaian tingkatan bahasa “sor-singgih” (halus-kasar) yang dipadukan begitu saja dengan bahasa Bali Age.
Masyarakat Tenganan adalah salah satu orang-orang Bali Age. Menurut Gori Sirikan mereka adalah keturunan orang-orang yang dibawa oleh Rsi Markendya.[9] Mereka mulai memeluk Hinduisme, madzad Indra karena terpengaruh oleh Prabu Maharaja Bima yang bergelar Çri Bayu, seorang rohaniwan yang dibawa oleh Raja Jawa Çri Maharaja Jaya Çakti tahun 250.[10] Dengan demikian, cerita rakyat di atas dimaksudkan untuk menegaskan kepada penikmatnya, bahwa sebelum ditaklukkan oleh kekuasaan Hindu (Ciwa), masyarakat Desa Tenganan memiliki kebudayaan asali, yakni madzad Indra yang berbeda dengan aspek-aspek kultural Hindu (Ciwa). Lebih dari itu, melalui cerita itu mereka menyerukan kepada masyarakat Tenganan untuk tidak menyembah kekuatan para dewa Hindu (Ciwa) yang bersemayam di palinggih sanggah, meru, dan pura puseh, karena bisa jadi penghuninya bukan dewa sebenarnya melainkan dewa siluman atau makhluk yang statusnya lebih rendah dari dewa, yang dalam cerita itu disimbolkan dengan seekor burung.
Lebih jauh dari itu, keberadaan masyarakat Tenganan semestinya dilihat pula dalam kaitannya dengan situasi pasca kejatuhan kekuasaan raja Bali Çri Asta Sura Ratna Bumi Banten ke tangan Majapahit pada kedalaman 667 silam (1343 M) Kerajaan Majapahit. Dalam kehidupan keagamaan peristiwa ini dapat disebut sebagai berakhirnya masa keharmonisan agama Siwa-Buddha atau masa keberagaman agama-agama di Bali. Para penganut agama-agama lama yang beragama secara merdeka merasakan diri mereka terjajah setelah rezim Majapahit melakukan restrukturisasi agama. Menurut R. Goris, restrukturisasi agama terjadi pada kedalaman 660 tahun silam (1350 M), dengan cara mengubah agama Hindu Bali menjadi Hindu Jawa Bali. Peristiwa itu antara lain ditandai dengan pemisahan warga masyarakat menjadi triwangsa dan sudra. Triwangsa adalah bangsawan Jawa, sedangkan sudrawangsa semua orang di luar bangsawan Jawa (triwangsa); dan para sudra yang datang dari Jawa disebut sudra jati.[11] Dalam prakteknya, golongan triwangsa memiliki hak istimewa dalam kehidupan keagamaan, sehingga golongan sudrawangsa, terutama yang tidak sepakat dengan agama negara bentukan penguasa Majapahit, yaitu Saiwasiddhanta melakukan perlawanan melalui dongeng-dongeng. Dengan demikian, cerita rakyat “Pan Botoh Lara” semestinya dikaitkan dengan kondisi Desa Tenganan sebagai desa tempat pelarian para bangsawan dan rakyat jelata kerajaan Bali yang tersisihkan oleh Majapahit, yang sekaligus pula membawa adat dan agamanya. Melalui analisis itu, akhirnya dapat dimengerti alasan PHDI yang menganut paham Saiwasiddhanta, yang berada di bawah payung kekuasaan Golongan Karya pada dekade 1980-an merasa berkepentingan menaklukkan musuh bebuyutan leluhur mereka di desa-desa Baliage, dengan cara memaksakan pelaksanaan konsep Hindu-Jawa pada perhitungan jatuhnya hari raya dan penggunaan pamangku sebagai pemimpin dan penyempurna upacara adat.[12]
Sama dengan Tosning Dadap Tosning Presi, kedua cerita rakyat ini (Pan Botoh Lara dan Mayadenawa) juga diproduksi oleh orang yang memiliki kekuasaan dan pemikiran kreatif. Mereka membangkitkan relasi kekuasaan dan pengetahuan antara kelompok orang yang mengangkat diri mereka, dan mengaturnya melalui cerita itu. Akan tetapi berbeda dengan Tosning Dadap Tosning Presi, yang masih memberikan peluang bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pemikiran kreatif itu adalah kelompok elite. Dalam cerita “Pan Botoh Lara” khususnya, peluang kelompok elite tampaknya tidak begitu menonjol. Dari alur cerita Pan Botoh Lara, tampak jelas cerita itu betul-betul berasal dari rakyat jelata, yang menolak konsep Hindu, terutama ajaran karmaphala. Sesuai dengan konsep karmaphala, siapapun yang menjadi korban kelicikan atau kejahatan dalam sebuah tragedi pasti akan memperoleh pahala baik. Dalam cerita itu, Pan Blandang adalah korban penipuan burung Curik. Oleh kareba itu sesuai konsep karmaphala, penyiksaan yang dilakukannya terhadap burung itu seharusnya dilihat sebagai pahala dari perbuatannya sebagai penipu, namun di akhir cerita yang menjadi korban penderita adalah Pan Blandang, bukan burung curik. Dengan demikian, Pan Blandang adalah refresentasi masyarakat terjajah yang tidak berdaya menghadapi kekuasaan para penjajah, yang meraih kekuasaan dengan cara menipu.
Melalui cerita itu, pengarang ingin menjelaskan bahwa orang-orang Bali Baliage berbeda dengan Bali daratan. Orang-orang Baliage di desa Tenganan memang tidak memeluk agama Tirta (agama Air Suci) atau disebut juga agama Maborbor (agama pembakaran jenazah). Mereka juga tidak mengenal pembagian golongan maupun kasta, meskipun di Desa Tenganan terdapat pembagian yang kelihatannya serupa. Dalam hal kebahasaan, masyarakat Desa Tenganan juga tidak mengenal bahasa tinggi (halus) atau bahasa rendah (kasar).[13] Dengan demikian, bisa dimengerti di Desa Tenganan muncul dan berkembang cerita rakyat yang menyangsikan atau menggugat keabsahan kekuasaan konsep palinggih sanggah, dewa, meru, dan pura puseh. Masuknya pengaruh Hindu (Çiwa) ke dalam komunitas orang-orang Baliage Tenganan yang bermadzad Indra, dengan demikian, dapat pula disebut sebagai sebuah keterputusan (dicontinuity) sejarah, yakni hilangnya sebuah masa sejarah madzad Indra digantikan oleh sejarah Hindu (Çiwa). Pergantian itu terjadi melalui dominasi, artinya suatu pengaruh yang dipaksakan dengan jalan kekerasan.[14] Sebagai akibatnya, tradisi Baliage menjadi tertekan. Akan tetapi seperti dikatakan oleh Freud bahwa sebuah peristiwa yang ditekan adalah sebuah peristiwa yang terlupakan, namun sebenarnya belum menghilang. Secara tidak sadar, peristiwa itu tetap kuat di dalam pikiran, untuk muncul kembali melalui jalan yang penuh teka-teki. Pikiran dan emosi yang tertekan itu akhirnya muncul dalam cerita rakyat yang secara sembunyi-sembunyi menyepelekan simbol-simbol Hindu seperti disebutkan di atas.[15]
Pikiran dan emosi yang tertekan itu juga dapat dilihat dalam cerita rakyat Tosning Dadap Tosning Presi. Dalam cerita ini tampak jelas, klen Dukuh kehilangan sejarahnya digantikan oleh sejarah dewa-dewa orang-orang Hindu, Çiwaisme, dengan dewa tertingginya Çiwa yang juga disebut Mahadewa, yakni sejarahnya para penakluk Bali yang beragama Ciwa.[16] Sejak berkuasa di Bali para pengikut Batara Mahadewa (pengikut agama Majapahit) memposisikan dirinya sebagai produsen dan sekaligus pengontrol agama dan kebudayaan Bali. Segala sesuatu yang menyimpang dari ajarannya adalah musuh, yang harus dilawan dan bahkan dibasmi. Oleh karena itu dalam sejarah Bali sering terjadi perang agama atau kasus-kasus kekerasan yang berlatar agama yang sudah lebur dengan adat. Salah satu kasus kekerasan agama, namun sudah dibungkus dengan mitologi adalah kisah Raja Mayadenawa.
Berbeda dengan Profesor I Nyoman Weda Kusuma, yang tidak menyebutkan latar belakang kisahnya, menurut Gora Sirikan, kisah Mayadenawa terjadi pada masa pemerintahan Raja Çri Candrabayasingha Warmadewa. Pada masa itu ada seorang raja Bali lainnya bernama Çri Mayadenawa yang beristana di Batanar dekat Desa Bedulu. Konon, raja ini tidak beragama, mengabaikan adanya dewa-dewa di Bali. Pada bulan Magha (Januari) Mayadenawa melarang rakyatnya melakukan persembahyangan di pura Dalempuri yang letaknya di Besakih untuk memuja Dewi Durga. Bersama dengan patihnya yang amat setia, Kalawong, dia duduk di depan Pura manik Mas untuk bertanya dan melarang rakyatnya yang sedang membawa sesaji ke pura itu.
Batara Mahadewa, sang penguasa Gunung Agung mengetahui keganjilan sikap Mayadenawa. Dia mengadukan persoalan itu kepada Paramasiwa di Gunung Semeru, Jawa Timur. Paramasiwa segera memerintahkan Dewa Indra supaya segera datang ke dataran Bali untuk menumpas Mayadenawa. Dewa Indra membawa laskarnya ke Bali. Mereka berkumpul di Pura Besakih, lalu bergerak menuju Desa Bedulu. Mayadenawa juga bersiap menunggu kedatangan musuhnya. Terjadilah pertempuran dan Mayadenawa dapat dikalahkan. Dari cerita itu muncul mitos Tirta Empul, air yang menyembur dari balik tanah, yang sampai sekarang dijadikan air suci. Dalam cerita disebutkan air itu meyembur dari tanah setelah Indra menancapkan dua batang tombaknya di sebelah air mancur beracun yang dibuat oleh Mayadenawa. Muncul juga mitos air sungai Petanu tercemar darah Mayadhanawa, sehingga Dewa Indra mengutuknya tidak boleh digunakan untuk kepentingan ritual selama 1700 tahun.[17] Peristiwa itu, menurut Gora Sirikan terjadi pada tahun 974 seperti terungkap dalam kitab “Pamancangah” milik klen Pasek. Gora Sirikan berani dengan tegas menyebutkan peristiwa itu sebagai perang agama antara penganut Budha Hinayana dan Mahayana di Bali, namun dalam prasasti-prasasti tidak pernah disebutkan ada seorang raja yang bernama Mayadenawa. Sirikan menduga, dia mungkin orang Baliage yang mengangkat diri menjadi raja untuk menentang kekuasaan Raja Çri Candrabayasingha Warmadewa. Analisis itu tentu didasarkan pada kepemilikan kitab “Pamancangah” yang berada di tangan klen Pasek, salah satu kelompok bangsawan Bali Kuno yang sekarang selalu melakukan perlawanan terhadap golongan bangsawan Bali Baru, penguasa sejak kekuasaan Majapahit di Bali.[18]
Apapun agama yang dianut oleh Mayadenawa apakah Buddha Hinayana atau Tantrayana aliran kiri, tak perlu dipersoalkan di sini. Demikian pula, tidak perlu dipersoalkan apakah Mayadenawa tokoh mitos atau historis; yang jelas, dalam realitas sejarah, kasus kehancuran kerajaan Bali Kuno dipicu oleh perbedaan aliran agama; jadi, perbedaan agama dijadikan alasan sebuah peperangan. Akan tetapi di balik alasan itu, bisa disebutkan tersembunyi relasi-relasi kekuasaan, yakni menciptakan sebuah peperangan. Tujuan berperang bukan semata-mata untuk memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga memperbanyak kawula, guna menopang sebuah negara teater seperti yang dikatakan oleh Geertz;[19] atau untuk menambah devisa bagi negara seperti yang diungkapkan oleh Henk Schulte Nordholt.[20]
Dominasi kekuasaan itulah yang dilawan oleh para bangsawan Bali Kuno melalui cerita rakyat. Analisis ini bisa dipahami, karena sejarah membuktikan begitu banyak kisah perlawanan yang mereka lakukan untuk membongkar atau menghancurkan dominasi bangsawan Bali Baru yang memuja Siwa. Ketika kekuasaan kelompok bangsawan Bali Baru masih kuat, perlawanan itu dilakukan melalui ceritra rakyat. Ideologi perlawanan mereka adalah pernyataan tidak puas dengan dominasi bangsawan Bali Baru atas bangsawan Bali Kuno. Demi memperjelas adanya kecenderungan perlawanan seperti itu, silahkan lihat cerita rakyat Nang Poleng, yang mengisahkan protes rakyat kecil dari kelompok bangsawan Bali Kuno terhadap bangsawan Bali Baru (bangsawan bentukan Majapahit) yang oleh kekuasaan diberikan hak-hak istimewa dalam hal ritual. Cerita ini berkisar pada hukuman yang diterima oleh Nang Poleng (seorang sudrawangsa) di Neraka atas kesalahan anaknya (I Poleng) memilih tingkatan upacara pengabenan untuk dirinya. I Poleng mengupacarai roh ayahnya dengan memakai bade matumpang pitu, tirta dan kajang yang paling utama. Pendeta Ciwa tidak memenuhi permintaan itu, karena statusnya dari wangsa sudra yang tidak boleh memakai sarana upacara utama, sesuai dengan permintaannya. Akan tetapi I Poleng bersikeras dan berjanji akan menanggung sendiri segala resikonya tanpa melibatkan pendeta itu. Pendeta Ciwa itu pun menyanggupi permintaan I Poleng, namun akibatnya Nang Poleng dihukum di neraka.[21]
Demikianlah, tampak jelas ada perbedaan sudut pandang dan analisis antara cendikawan otodidak Gora Sirikan dengan cendikiawan akademis Faksas. Kedua Profesor Faksas itu tampak mengabaikan atau tidak menggunakan pendekatan arkeologis sebagai alat bantu analisis, seperti yang dilakukan oleh Sirikan, sehingga kisah Mayadenana dalam sudut pandang Profesor Weda Kusuma menjadi tidak berhubungan dengan fenomena keagamaan zaman sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan arkeologis, maka analisis terhadap cerita rakyat, terutama yang memiliki tendensi sebagai kisah perlawanan maupun yang diproduksi untuk penjaga gawang status quo, misalnya kisah kisah perdamaian agama-agama di Pura Samuan Tiga, akan menjadi lebih komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan arkeologis, akan ditemukan data-data pengakuan raja-raja Bali Kuno terhadap keanekaragaman agama seperti diterangkan di bawah ini. Hasil penggalian sejarah Bali pada kedalaman yang lebih silam daripada lokasi kedalaman kekuasaan Majapahit, yaitu antara 681 sampai 1210 tahun silam (1329-800 M) menunjukkan adanya “fosil-fosil” kehidupan keagamaan yang berbeda dengan masa-masa kekuasaan Majapahit di Bali seperti diterangkan di bawah ini.
Pendekatan Arkeologis yang dilupakan
Berbeda dengan kondisi keagamaan pada masa kekuasaan kerajaan bentukan Majapahit di Bali, hegemoni kelompok mayoritas tidak tampak ke permukaan pada peninggalan sejarah Bali 681 silam. Menurut Goris, yang menjadi Raja Bali pada kedalaman 681 tahun adalah Bhatâra Çri Asta-asura Ratna Bhûmi Banten.[22] Shastri tidak sepakat dengan sebutan ini. Menurutnya, raja itu bernama Çri Asta-sura Ratna Bhûmi Banten, yang artinya seorang putra dewa yang menjelma di pulau Bali.[23] Nama itu ditemukan pada sebuah arca di Pura Tegeh Koripan di Gunung Penulisan dan mulai berkuasa pada tahun 1329.[24] Kekuasaan raja inilah yang dapat direbut oleh Majapahit.
Gora Sirikan berpendapat Çri Asta-sura ratna bhûmi banten adalah keturunan dinasti Warmadewa. Pada masa pemerintahannya, di Bali terdapat Wihara Bahung di lereng Gunung Agung, yang merupakan tempat pertapaan Mpu Dangudhyaya Kangka, seorang penasehat raja Bali. Pada kedalaman itu ada pula rumah pendeta Kaçaiwan (untuk agama Çiwa) yang meliputi Air Garuda, Air Gajah, Antakunyarapada (Rantakunyarapada), Binor, Dharma Anyar, Haritanten, Kanyabhuwana, Kusumadanta, Lokaçwara, Suryamandala, dan Udayalaya. Ada pula rumah pendeta agama Buddha yang disebut Kasogatan yakni, Bajraçikhara, Wihara Bahung, Buruan, Canggini, Dharmarya, Kuçala, Kuti-Hanar, Lwa Gajah, Nalada, dan Waranasi. Kebanyakan rumah-rumah pendeta ini tidak diketahui lokasinya sekarang. [25]
Di bawahnya lagi, pada kedalaman 710 tahun yang lalu (1300 M), ditemukan “fossil” Kebo Parud yang beragama Wajrayana, yakni agama Buddha aliran Tantrisme. Keberadaan agama ini sudah mendapat pengakuan di Bali pada kedalaman 887 sampai 855 tahun silam pada zaman raja Jaya Çakti (1133-1155 M). Aliran ini sangat condong pada ilmu sihir atau ilmu gaib. Pemimpin tertinggi aliran ini adalah Raja Singhasari, Krtanegara. Raja ini sering melakukan kegiatan-kegiatan upacara yang menyangkut agama ini.[26] Gusti Ayu Surasmi, berpendapat fossil Kebo Parud adalah sebuah arca Bhairawa di Pura Kebo Edan, Pejeng, Gianyar, yang menunjukkan adanya latihan-latihan dan upacara tantrayana di Bali.[27] Menurut Shastri, latihan-latihan wajrayana yang dilakukan oleh para pegawai kerajaan Singhasari berlanjut dengan pendirian sebuah biara (asrama) yang letaknya berdekatan dengan Ratna Kunnyarapada, sebuah asrama para pendeta Çiwa. Fakta ini terungkap dalam buku “Negara Kertagama,” yang ditulis oleh Prapanca. Di dalam buku ini dikatakan ada pendeta Buddha besar yang berdiam di Bedaulu, di Luwing Gajah, yang tidak pernah angkara murka. Luwing Gajah adalah tempat di sekitar Air Gajah atau Goa Gajah, yang merupakan bagian dari asrama Kunyarapada. Shastri berpendapat, kehadiran para pendeta Buddha ini mengakibatkan terjadinya persiangan antara pemeluk agama Buddha dengan Çiwa.[28]
Apabila digali lebih dalam lagi, pada kedalaman 726 tahun (1284 M) Raja Krtanegara dari kerajaan Singasari berhasil menaklukkan Bali.[29] Saat itu rakyat Bali mungkin sedang diperintah oleh Raja Bhatâra Çri Paraméçwara Çri Hyang ning, Adidéwa,[30] yang sudah berkuasa di Bali pada kedalaman 750 tahun (1260 M).[31] Krtanegara adalah seorang raja yang beragama Buddha aliran Warnamarga atau golongan kiri, yang umumnya disebut Buddha Tantrayana. Para pengikut golongan ini banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tertulis dalam buku “Sanghyang Kamahayanikan” dan “Tantra Wajra Dhatu Subhuti.” Kedua buku ini berisikan uraian mengenai tatacara upacara dan cara-cara hidup yang diajarkan oleh aliran ini. Ajaran ini tidak boleh diajarkan atau diberitahukan kepada seseorang yang tidak masuk dalam lingkungan mandala. Dalam buku “Negara Kertagama” dan “Pararaton,” aliran ini disebut dengan istilah Çiwa-Buddha. Shastri berpendapat penamaan ini tidak tepat, karena aliran ini tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Ia menduga penamaan ini punya latarbelakang politik, yakni untuk menyatukan pengikut agama Çiwa dan Buddha. Krtanegara bermaksud menarik perhatian para pendeta Çiwa, yang saat itu tidak pernah melakukan upacara-upacara aliran ini, namun pengaruhnya tampak kuat dalam kehidupan keagamaan mereka. Ada pula yang menyebut sekte ini dengan istilah “Bhairawa.” Nama Dewa Bhairawa juga dipuja di Tibet. Di nusantara, dewa ini dipuja oleh orang-orang yang percaya dengan adanya ilmu sihir.[32] Apakah Krtanegara yang mewariskan aliran ini di Bali? Siapa yang berkuasa di Bali ketika Jawa berada di tangan Krtanegara? Tidak ada yang mampu menjawabnya, jelasnya, setelah ditaklukkan oleh Krtanegara tahun 1284, dalam waktu yang cukup lama tidak ditemukan lagi prasasti di Bali.
Dikedalaman 806 tahun (1204 M), Bali berada di bawah pemerintahan raja Çri Dhanâdhirâja dan istrinya Bhatâra Çri Dhanadewi. Pada masa itu sudah ada perayaan-perayaan yang dilangsungkan di setiap pura yang terdapat dalam wilayah desa dan kewajiban penduduknya menyelenggarakan upacara-upacara pada waktu yang sudah ditentukan. Disebutkan pula sebuah pura bernama “Hyang Wukir,” yang merupakan tempat pemujaan warga setempat. Pada bagian akhir prasasti yang dikeluarkan pada zaman itu berdapat lukisan Bhatara Guru bertangan empat di dalam sebuah lingkaran yang merupakan pancaran cahaya terang.[33] Prasasti ini juga menyebutkan suatu upacara pada Magha Mahanawami dan odalan di Pura Hyang Ukir di Gunung. Upacara ini dirayakan dengan sangat meriah dan lampu-lampu dinyalakan di sekitar desa.[34]
Pada kedalaman 811- 895 tahun (1119 – 1115 M) diberitakan perkara yang terjadi antara penduduk desa Air Tabar dengan pertapaan (dharma) Indrapura. Penduduk desa Air Tabar memohon agar mereka dibebaskan dari tugas menyumbang pada pertapaan Indrapura, karena mereka sudah memikul kewajiban melakukan upacara terhadap Betari Bukit Tunggal. Raja mengabulkan permohonan ini dengan catatan bahwa mereka wajib membayar pajak kepada pemerintah. Persoalan ini sudah ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan pada kedalaman 1029 pada zaman Çri Maharaja Wijaya Mahadewi tahun 983 M dan pada kedalaman 1096 silam zaman Singha Mandawa tahun 914 M.[35] Dikedalaman 829 (1181 M) disebutkan penduduk Batur dan Cempaga mengajukan permohonan kepada raja supaya diizinkan berpindah keyakinan dari semula memuja Ganapati ring Tumpak Hyang beralih ke dewa-dewa di Gunung Batur. Permohonan ini dipenuhi oleh raja. Demi menjaga wibawa Ganapati, raja membebaskan para pemujanya dari kewajiban membayar pajak, mereka hanya diwajikan memberikan sumbangan kepada pertapaan Dharma Anyar. Dulu desa ini mungkin terletak di dekat Kintamani, namun sekarang termasuk wilayah Bangli.[36] Pada kedalaman itu juga disebutkan nama pertapaan Ratna Kunyarapada. Nama ini serupa dengan Anta Kunyara sudah ditemukan dalam prasasti Lutungan pada kedalaman 939 (1071 M).[37] Shastri menyamakan arti Anta Kunyara dengan Ratna Kunyarapada. Asrama ini merupakan kenangan dari asrama Kunyara Kuya Maharesi Agastya yang terletak di Mysore di India Selatan.[38]
Pada kedalaman 833 – 855 silam (1177 – 1155 M), Raja Ragajaya sudah menggunakan kitab undang-undang Uttara Widdhi Balawan dan Raja Wacana (Raja Niti) sebagai panduan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kitab ini juga sudah dipakai oleh raja-raja sebelumnya, seperti Sakalendu Kirana yang memerintah pada pada kedalaman 911 (1099 M). Pada masa pemerintahan raja Ragajaya, agama Çiwa dan Buddha berkembang dengan baik di seluruh Bali. [39] Pada periode itu, terutama masa pemerintahan Raja Jayapangus, sudah disebutkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan mati atau kematian yang disebabkan oleh salah pati (kematian secara tidak wajar), yang penetapannya hingga sekarang masih ditaati oleh masyarakat Bali-Hindu. Saat itu sudah pula disebutkan prihal kepercayaan masyarakat desa yang mendiami daerah-daerah pegunungan, yang seringkali berlainan dengan yang dianut oleh kaum brahmana dan para raja di Bali daratan.[40] Di Desa Sawah Gunung pada sebuah pura yang bernama Pangukur-Ukuran disebutkan antara lain “Mpukwing Dharma Hanar” dan “Ratnakunyarapa, yakni pertapaan Dharma Anyar dan asrama Ratnakunyapadapa, yang sudah ada pada zaman Anak Wungsu.[41]
Pada kedalaman 860 tahun silam (1150 M), dijelaskan prihal sebuah pertapaan yang disebut Wihara Bahung yang terletak di lereng Gunung Agung.[42] Dalam prasasti ini diputuskan pula masalah yang terjadi di desa Bantiran dan raja disebutkan dengan gelar Sira Prabhu Saksat Harimurti Jagadhita Karana,[43] sehingga semakin mempertegas raja Jaya Çakti beragama Wisnu, seperti terlihat dari kata Harimurti yang sama artinya dengan Dewa Murti atau Dewa Wisnu. Dikedalaman 877 tahun silam Bali diperintah oleh Çri Maharaja Jaya Çakti (1133 – 1150 M) yang menganut agama Wisnu, yang dapat dilihat dari nama gelarnya yakni Sira Prabhu Saksatnira Wisnu Murti Muktyasa. Prasasti ini menyebutkan pula nama desa Kedisan, Bwahan, dan Air Tabar, yang terletak di sekitar Danau Batur. Disebutkan pula nama Sirang Keçaiwan Mpung Kweng Dharma Anyar. Istilah Dharma Anyar dijumpai pula dalam prasasti yang dikeluarkan oleh raja berikutnya, Jaya Pangus dan sudah disebutkan pula pada zaman Anak Wungsu.[44] Fakta ini menunjukkan, biarpun beragama Wisnu, namun Jaya Çakti tetap menghormati agama Çiwa, sebab Dharma Anyar adalah bagian dari agama itu. [45] Raja Jaya Çakti juga menghormati para bhiksu yang digambarkan ikut menghadiri suatu sidang pengadilan. Di antara peserta sidang disebutkan pula nama-nama Aghore Swara, seorang pengikut aliran Wajrayana (agama Buddha aliran Tatraisme) dan seorang yang bernama Wajra Çikara. Sidang memutuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan salah pati (mati secara tidak wajar) di tiga desa itu.[46]
Pada kedalaman 891 (1119 M) rakyat Bali berada di bawah masa pemerintahan Raja Çri Çûrâdhipa yang menganut agama Wisnu, yang terlihat dalam gelar “Çri prabhu sakti Wisnu murti jagat palaka sakala Candra ditya.” Masalah yang dibertakan dalam prasasti ini adalah perkara yang berkaitan dengan pertapaan Sukamerta. Persoalan ini sebenarnya sudah pernah diselesaikan oleh raja Aji Tawanendra Warmadewa pada kedalaman 933 tahun silam (1077 M). Pada periode ini raja Bali sudah semakin jauh meninggalkan konsepsi agama Çiwa-Buddha.
Pada kedalaman 909 – 922 tahun silam (tahun 1101 -1088 M) [47] ditemukan dua buah arca, yakni arca Hariti yang berisikan tulisan “Betara I Banyu Pelasa” dan arca Parwati yang bertuliskan “Sang ring Guha.” Oleh karena saat ditemukan kedua arca ini sudah berpindah dari tempatnya semula, maka sukar untuk menentukan di mana letak Banyu Plasa yang sebenarnya. Lebih menyulitkan lagi, karena arca Hariti yang ditinggalkan oleh Ratu Pingit berbeda dengan yang ditemukan di Goa Gajah.[48] Gora Sirikan berpendapat, dua buah arca ini ditemukan di Pura Penataran Panglan di desa Pejeng, yang masing-masing ditulis tahun 1091. Dari tulisan ini, muncul penafsiran, raja ini pernah bertapa di sebuah goa dan setelah meninggal abu jenazahnya dimakamkan di tepi sungai Plasa. Akan tetapi tidak ada satu pun yang mengetahui di mana letak sungai ini. Ada yang menafsirkan goa tempat pertapaannya terletak di sebelah barat desa Pejeng, sebab di tempat ditemukan sebuah bekas pertapaan dan sebuah candi bernama Kelebutan. Andaikan kedua arca ini dapat dinilai sebagai lambang kebesaran raja, maka dapat dikatakan agama yang diabut oleh raja ini adalah Indra dan Çiwa, sebab Hariti sama dengan Indra, sedangkan Parwati adalah çaktinya Çiwa. Biarpun demikian, yang dominan adalah agama Çiwa, sedangkan agama Buddha terus mengalami kemerosotan. Apakah raja ini menghormati Çiwa-Indra? Jawabannya dapat dilihat dalam prasasti yang ditemukan pada kedalaman 912 (1098 M). Dalam prasasti ini muncul nama Paduka Çri Maharaja Gon Karunia Pwa Swabhawa Çri Saksatnira Harimurti Jagatpalaka Nityasa. Harimurti artinya penjelamaan Wisnu. Dalam sapatha (sumpah) prasasti ini disebutkan nama Rsi Agastya dan dewa-dewa lainnya dalam agama Hindu. Tidak satupun disebutkan nama-nama yang berhubungan dengan agama Buddha.[49] Dengan demikian, dapat dikatakan raja ini beragama Wisnu, namun menghormati juga Çiwa-Indra.
Dengan menggali lebih dalam lagi pada kedalaman 922 – 931 tahun silam (1088 – 1079 M) ditemukan “fossil” saat rakyat Bali berada di bawah kekuasaan Çri Maharaja Çri Walaprabhu.[50] Walaprabu adalah seorang pengikut agama Wisnu. Hal ini terbukti dalam bunyi prasastinya antara lain berbunyi “Tekyaen pwa paduka Çri maharaja wisnu murni saksat jagat palaka.” Shastri berpendapat aliran Wisnu sudah berkembang di Bali pada masa pemerintahan Marakata pada kedalaman 984- 988 (1022-1026 M). Aliran ini juga dianut oleh Airlangga, seperti terbukti dari lambang yang digunakannya, yakni seekor burung garuda.[51] Dengan demikian, pada periode ini mulai terjadi proses trasnsformasi dari agama Çiwa ke agama Wisnu. Para pemuja kemuliaan Wisnu menyebut diri mereka sebagai kaum Waesnawa. Komunitas ini terbagi menjadi dua golongan yakni Bhagawata dan Pancarata. Keduanya sekarang sudah tidak ada lagi di Bali, namun sisa-sisanya masih dapat dilacak, karena kemuliaan ajarannya masih dipelihara dengan baik oleh kelompok Sengguhu. Biarpun mereka dianggap sebagai golongan rendah, namun mereka diberikan tugas istimewa, yakni diwajibkan turut serta dalam memimpin dan menyempurnakan upacara keagamaan untuk kepentingan umum yang dilangsungkan secara besar-besaran. Saat melakukan pemujaan, mereka menggunakan lambang kebesaran Wisnu, antara lain kulit keong sebagai çangka yang disebut sungu, gantha (wajra), dan cakra. Pujaan mereka diarahkan ke dasar bumi yang merupakan kediaman makhluk-makhluk gaib pendukung dunia.[52]
Lebih ke bawah lagi, masih ditemukan banyak bukti kehidupan keagamaan pra kekuasaaan Majapahit di Bali yang menunjukkan adanya pertalian antar-agama, terutama Siwa dan Buddha. Dengan melihat fenomena itu, maka dapat dipahami di era kekuasaan raja-raja bentukan Majapahit di Bali bermunculan wacana untuk menaklukkan pengaruh agama Buddha, demi tercapainya satu kekuasaaan di bawah naungan Saiwasiddhanta, seperti yang diterangkan di bawah ini.
Teori Dharma Sunia yang terlupakan
Dengan mempelajari fenomena keagamaan pada zaman Bali Kuno, maka dapat dipahami alasan-alasan tersembunyi Danghyang Nirartha menciptakan lontar Dharma Sunia. Lontar ini ditujukan kepada mereka yang ingin mendapatkan kemenangan dengan mengalahkan musuh (dalam badan) sendiri dan yang ingin mencapai lingga, suatu kedudukan pendeta loka-paracraya yang dipercayai oleh penganut-penganutnya Dalam Lontar ini, Danghyang Nirartha mengajarkan umat Hindu supaya melakukan perihal Buddha, yang artinya bathin. Buddha adalah jiwa atau sinar jiwa yang mempunyai hubungan gaib dengan Parama Buddha yaitu jiwa yang maha besar atau Tuhan yang Esa. Gerak Buddha akan melahirkan buddhi dan perkembangan buddhi menjadi buddhaya. Jika cipta ditujukan dengan betul-betul kepada Buddha, tentunya dengan yoga, sehingga dapat menguasai bathin yang suci, niscaya unsur bayu, cabda dan hidhep akan musna dengan sendirinya dengan secara rahasia. Apabila telah datang tanda-tanda yang sedemikian itu, maka jiwa (Buddha) telah mulai memasuki alam bahagia.
Rahasia ajaran Dharma Sunia, menurut I Gusti Bagus Sugriwa melingkar dalam bayu, cabda dan hidhep. Oleh karena itu, orang yang ingin melakukan perihal Buddha, harus berupaya kuat dan yakin agar dapat menguasai ketiganya. Dalam praktik sehari-harinya dapat dilaksanakan seperti minum obat dokter, tiga kali dalam sehari (malam, pagi, siang), yakni (i) pada waktu malam bila akan tidur; (ii) pagi-pagi baru sadar dari tidur; dan (iii) siang hari waktu istirahat kerja. Setiap kali melakukannya, dibutuhkan sekurang-kurangnya 10 atau 15 menit. Caranya bisa dengan duduk atau terlentang tidur. Pertama, harus diam (menguasai cabda); kedua, tenangkan bayu, jangan gelisah atau jangan bergerak ke sana ke mari, dan jangan menggoyang-goyangkan kaki; ketiga, masukkan pikiran (ke dalam di sendiri) jangan sampai terpencar memikirkan sesuatu yang ada di luar, pusatkan pikiran dalam jiwa. Jika sudah terbiasa melakukannya, lambat laun akan mendapat kemajuan, semangat jiwa itu akhirnya dapat memasuki alam nirbana. Jiwa yang telah memasuki alam nirbana, tidak merasakan mati atau hidup, tidak merasakan baik atau buruk, suka atau duka miskin atau kaya, bangsawan atau hina yang sifatnya tidak abadi. Besarnya memenuhi alam tetapi tidak kelihatan secara nyata.
Orang yang telah berhasil menjalankan teori Dharma Sunia tidak akan gelisah berpergian, tidak merasakan diri ada di bawah, di atas atau di luar. Titik perhatian mereka adalah kesepian (sepining pamrih). Mereka adalah orang yang telah berbatin suci, sepi keinginan menuju kepentingan diri sendiri, yang dipentingkan hanyalah keheningan bathin. Orang yang semacam ini telah menyelesaikan pelajaran ajaran agama. Ia boleh tidak melakukan upacara, boleh tidak memuja dengan weda, mantram, dan lain sebagainya, karena telah dapat menunggal kepada Tuhan. Apa yang dikatakan tidak ada oleh orang lain, bagi dia ada dan yang dikatakan hilang, bagi dia tidak hilang. Orang yang semacam ini dapat memancarkan cahaya peri kemanusiaan yang adil (maharddhika) di dunia.
Bedasarkan lontar Dharma Sunia, maka bisa disebutkan bahwa kehidupan tanpa upacara, tanpa pura, dan mantram yang diungkapkan dalam kisah Mayadenawa bukan sesuatu yang mengada-ada. Dengan demikian kisah Mayadenawa sekaligus bisa dipahami sebagai upaya dekonstruksi pasukan Dewa Indra terhadap teori Dharma Sunia, sehingga keberadaannya hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Menurut Ida Bagus Jelantik (staf Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia), lontar Dharma Sunia merupakan bacaan wajib bagi para calon pedanda.[53] Sebelum menjadi pendeta, seorang walaka diwajibkan menyalin lontar itu. Lontar Dharma Sunia yang oleh Ida Bagus Dharma Palguna disebutkan disalin dari sumber aslinya pada tahun 1734,[54] baru dapat dibaca oleh masyarakat luas pada tahun 1950. Saat itu I Gusti Bagus Sugriwa mempublikasikan hasil terjemahan dan tafsiran atas lontar itu pada Damai.[55]
Kehadiran terjemahan lontar Dharma Sunia relatif tidak ada pengaruhnya bagi perkembangan praktek-praktek keagamaan di Bali pasca kemerdekaan. Pelaksanaan upacara keagamaan yang mengutamakan ritual daripada hakekat agama justru semakin semarak yang diawali dengan pelaksanaan upacara Pancawalikrama tahun 1960 dan Ekadasarudra tahun 1963. Seorang sarjana asal Bali lulusan Santiniketan (India) mengkritik fenomena keagamaan Bali di harian Suara Indonesia pada tahun 1961. Sarjana itu (konon, bernama Ida Bagus Mantra) mengatakan keadaan agama Hindu Bali masih sangat terkebelakang jika dibandingkan dengan agama-agama besar lainnya di dunia. Lebih jauh lagi, sarjana lulusan India itu mengatakan, agama Hindu di Bali agak mengecewakan karena tidak memiliki ketentuan, sehingga ada yang bersembahyang kepada nenek moyang, roh-roh jahat, para sanghyang, misalnya Siwa, Brahma, Iswara, dan sebagainya.[56]
Biarpun sudah diupayakan sekuat tenaga sejak 1920-an, namun perjuangan para intelektual memisahkan adat dan agama mengalami kegagalan pada tahun 1970-an dan bahkan hingga sekarang. Menurut Anandakusuma, kegagalan itu disebabkan karena para elite agama tidak mengindahkan kritikan sarjana lulusan India itu, sehingga agama Hindu di tahun 1970-an berada dalam tingkatan terendah, bersifat primitif. Anandakusuma sepakat dengan pemikiran sarjana lulusan India itu, bahwa agama Hindu di Bali belum setingkat dengan agama-agama lainnya. Hal itu menurut Anandakusuma terjadi karena rendahnya tingkatan agama Hindu yang disebabkan oleh latar belakang sejarah kebudayaan Bali maupun Jawa sebelum terkena pengaruh India yang bersifat primitif. Kesusasteraan yang ada di Bali di tahun 1970-an, menurut Anandakusuma adalah kelanjutan hasil olah pikir penduduk Jawa pra-Hindu dan dunia Hindu yang masuk ke Jawa sejak abad pertama. Dilihat dari sudut filosofi, di saat kedatangannya ke Jawa, agama Hindu menurut pendapat Anandakusuma juga masih bersifat primitif. Pada waktu kebudayaan India sudah mencapai kemajuan, justru hubungan Jawa dengan India sedang terputus karena masuknya kekuasaan Barat.[57]
Anandakusuma lebih jauh mengatakan, agama Hindu di Bali di awal tahun 1970-an, tidak bisa disamakan dengan agama Hindu di India. Ia memberikan contoh, orang Bali Hindu yang mengaku memiliki Veda yang bagi orang-orang India sudah dikategorikan sebagai Veda klasik dan harus disimpan di museum. Contoh lain, masih menurut Anandakusuma, di Bali tidak dikenal Upanisad yang pada tahun 1970-an justru sangat penting artinya bagi umat Hindu di India. Sementara di Bali hanya dikenal Brahmanas. Menurut Anandakusuma, Upanisad yang sudah mencapai tingkatan filosofi tinggi itu, dalam beberapa hal bertentangan dengan Brahmanas yang lebih mengutamakan ritual. Filosofi agama Hindu di Bali juga dinilai oleh Anandakusuma sangat rendah karena hanya dapat dicapai melalui korban. Dengan demikian, menurut Anandakusuma agama Hindu di Bali kehilangan pengemudi jiwa ke arah kesempurnaan, sehingga menjadi agama yang sangat materialistis dan hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang kaya. Agama Hindu pun dalam pengamatan Anandakusuma akhirnya hanya memperkaya orang yang sudah kaya dan memiskinkan orang-orang yang miskin, karena dipengaruhi oleh adaya sesaji yang megah-megah dengan menghabiskan uang bernilai ribuan, padahal orang-orang desa melakukan upacara dengan cara mengorbankan harta benda hanya karena mengikuti golongan elite. Atas dasar itu, Anandakusuma mengatakan agama Hindu Bali harus segera ditinjau ulang.[58] Demi kesejahteraan Pulau Bali di masa depan, Anandakusuma juga menyarankan supaya umat Hindu di Bali secara jujur bersedia membuang sifat-sifatnya yang kurang baik atau gemar mencari keuntungan untuk diri sendiri atau golongan sendiri. Dengan demikian rasa persatuan, saling menghargai akan dapat diwujudkan dan cita-cita menjadikan Bali yang indah dengan penduduknya yang aman sentosa, agama yang berjalan dengan baik akan dapat tercapai, dan pura-pura atau kayangan-kayangan tidak dijadikan sebagai arena perjudian.[59]
Semua kritikan yang disampaikan oleh Anandakusuma dan orang-orang yang sepemikiran dengannya, tidak sampai mempengaruhi sikap pengurus Parisada Hindu Dharma (sekarang PHDI) terhadap praktek-praktek keagamaan di Bali. Demi menyukseskan Pelita I mereka tetap menerjemahkan agama Hindu sebagai ritual, karena dengan cara itu kesinambungan pariwisata Bali tetap terjaga. Di sisi lain, secara tidak langsung agama Bali warisan zaman prasejarah yang sudah mengalami osmosis menjadi agama Hindu Bali dapat dilestarikan, ditegakkan atau dipertahankan di tengah-tengah kenikmatan industri pariwisata dan usaha modernisasi yang dilakukan pemerintah. Sebagai konsekuensi atas sikap itu, maka kepemimpinan atau kepengurusan Parisada Hindu Dharma akhirnya selalu dipegang oleh orang-orang yang sepakat bahwa agama Hindu adalah ritual. Penguasaan sepihak itu mengakibatkan keputusan-keputusan keagamaan yang melibatkan umat akhirnya dikuasai oleh sekelompok orang, seperti terlihat dalam kongres Parisada Hindu Dharma sebelumnya.
Sekarang, bandingkan dengan apa yang Faksas pada era 1970-an. Keberadaan pariwisata budaya justru mendapat dukungan dari Faksas. Pada tahun 1974, I Gusti Ngurah Bagus memperkuat kesimpulan McKean, seorang dosen tamu Faksas, bahwa industri pariwisata tidak hanya mengarah pada hal-hal yang negatif, namun banyak juga yang positif, yang bermanfaat bukan saja bagi masyarakat di Bali tetapi juga Indonesia. Pengaruh positifnya, menurut I Gusti Ngurah Bagus bukan hanya berupa pembukaan lapangan kerja, meningkatnya penghasilan masyarakat, tetapi juga perkembangan dan pemeliharaan kebudayaan Bali. Para wisatawan yang membutuhkan sesuatu yang khas Bali, dalam pandangan Ngurah Bagus telah merangsang munculnya kreativitas dan loyalitas.[60]
Dukungan kedua ilmuwan di atas, McKean dan I Gusti Ngurah Bagus, tampaknya dijadikan sebagai pembenar oleh pemerintah daerah dalam mengelola industri pariwisata Bali dalam Pelita II, tahun 1974-1979. Program Pelita II menekankan pada pengembangan sarana dan prasarana obyek pariwisata, khususnya di Bali dan beberapa daerah tujuan pariwisata lainnya. Selain itu, dalam Pelita II juga dilakukan pembinaan kelembagaan dan organisasi unsur-unsur penunjang pariwisata supaya mampu menyangga pengembangan pariwisata baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Di Bali, inti pokok pengembangan wisata dikonsentrasikan pada hotel-hotel di Nusa Dua, Sanur dan Kuta.[61]
Sejak itu pariwisata Bali tumbuh dengan dahsyat, keuntungan materi yang diperoleh darinya tidak ditopang oleh kekuatan moralitas, sehingga kapitalisme masuk ke pembuluh darah halus (kapiler), tinggal menunggu Fizza, McDonal, Kentucky Fried Chiken, melengkapi minuman ringan Coca Cola, Sprite, anggur, pir, dan apple luar negeri yang sejak lama sudah menjadi sesajen resmi di hari Galungan dan Kuningan, melengkapi.
Penutup
Revolusi Moralitas tampaknya bisa diawali dengan mengangkat dan mengakui eksistensi lontar Dharma Sunia sebagai salah satu sumber kebenaran dalam agama Hindu ala Bali. Akan tetapi harus diakui tidak semua orang (apalagi yang tidak terlatih) akan mampu mempelajari dan melaksanakannya, karena kecerdasan beragama setiap orang berbeda satu sama lain, sehingga.[62] Biarpun ada insan yang mampu melaksanakan tahapan-tahapan latihan yang ditawarkan dalam teori Dharma Sunia, namun sesuai dengan adanya pengaruh perbedaan kecerdasan beragama itu, maka tidak semua orang akan memperoleh hasil seperti yang diharapkan, yaitu bebas dari pelaksanaan upacara ritual dan hal-hal lain yang terkaitkan dengannya. Keterbatasan itu, tentunya tidak disikapi dengan cara membunyikan rapat-rapat atau mengaburkan makna yang terkandung di dalamnya. Lontar Dharma Sunia semestinya diajarkan dibangku sekolah, sehingga diperlukan buku Upadesa Tingkat Lanjut untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan beragama tingkat tinggi.
Sebelum menuju penerapan Teori Dharma Sunia, dalam upaya menuju menuju Revolusi Moralitas, kiranya ajaran agama Siwa-Buddha perlu dihidupkan kembali. Kedua agama ini, apabila dipadukan akan saling melengkapi satu sama lain. Agama Buddha lebih menekankan pada aspek pengolahan batin melalui meditasi, sedangkan agama Hindu ala Bali lebih pada ritual. Meditasi mengarah pada mengolahan jati diri dan potensi diri secara berkesinambungan, sedangkan ritual lebih pada harapan-harapan memperoleh berkat dari Hyang Ilahi dengan cara memberikan persembahan berupa sesaji. Faksas tentu mampu memberikan sumbang pikir dengan cara mempertajam teori dan metodologi penelitian teks agar sesuai dengan perkembangan pemikiran muthakhir. Akan tetapi tampaknya hal itu sulit terpenuhi karena, konon masih ada cendikiawan Faksas, terutama di tingkat S-3 yang mengelola pengetahuannya menjadi kekuasaan dengan menggunakan konsep etis, bukan kebenaran, dalam menentukan layak atau tidak sebuah tema disertasi yang akan dikaji oleh mahasiswanya. Pertimbangan etis dan tidak etis, dengan sendirinya bertolak belakang dengan sudut pandang keilmuan modern teori dekonstruksi. Semestinya mahasiswa diajarkan untuk membongkar kemapanan suatu wacana untuk menemukan titik-titik kepalsuannya, sehingga bisa dibenahi untuk kepentingan masa kini dan masa depan.
Demi mencapai tujuan itu, ada sejumlah hal yang perlu dibenahi oleh Faksas. (i) Memanfaatkan fungsi ruang Display, bukan sebagai ruang pamer artefak, melainkan sebagai media unjuk kebolehan para dosen dalam menghasilkan karya ilmiah. Semua hasil karya (terutama buku) semestinya dipamerkan dalam ruang Display; (ii) semestinya diterbitkan CV para dosen secara berkala (dua tahun sekali) sehingga dapat diketahui kemajuan yang telah dicapai seorang dosen dalam mengaktualisasikan konsep tridharma perguruan tinggi. Penerbitan itu akan dapat merangsang para dosen untuk berkarya supaya CV mereka tidak dipenuhi dengan deretan strip (kosong) atau dipenuhi dengan deretan “sebagai anggota tim peneliti,” tanpa pernah menjadi peneliti utama dan sebagai “peserta seminar” tanpa pernah sebagai pemakalah seminar. Idealnya sertifikat sebagai “pemakalah seminar” dijadikan salah satu persyaratan dalam kenaikan pangkat; (iii) faksas semestinya rela mengubah nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya, supaya payung keilmuannya semakin lebar sehingga memungkinkan membuka Jurusan Multi Media, Cinematografi, dan lain sebagainya.
Akhirnya, ada apa di balik setengah abad usia Fakultas Sastra dalam kaitannya dengan pidato Bung Karno. Jawabannya, tidak ada apa-apa. Pidato Bung Karno mengisyaratkan dengan mengedapankan ajaran-ajaran moralitas, Fakultas Sastra akan menjadi pewahyu rakyat yang selanjutnya akan mengubah jalan sejarah. Cita-cita itu terlalu berlebihan, karena seperti dikatakan oleh Michel Foucault, manusia tidak digerakkan oleh nilai-nilai yang mereka anut, melainkan berkompromi dengan wacana-wacana yang yang diberikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan.[63]
Nyoman Wijaya
Sejarawan, Fakultas Sastra Universitas Udayana
TSP Art and Science Writing | Kantor Sejarawan Profesional
Catatan:
Makalah dibawakan dalam acara Parum Param: Simposium Metamoia Moral Pembangkitan Jiwa Murni Bangsa (31 Mei 2010 di Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar).
Kunjungi Juga: http://tspkantorsejarawan.com



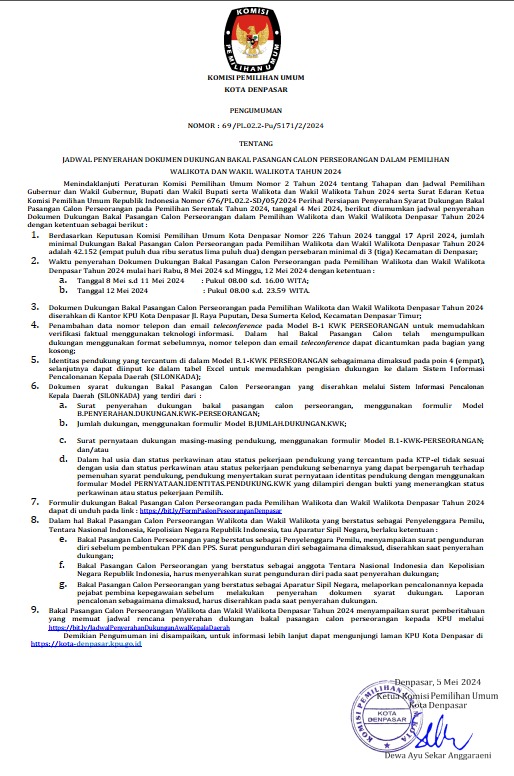









1 Komentar
mhn bisa dicopy ke email tsb diatas thks