KODE ETIK KEPANDITAAN : APAKAH PERLU?
Ilustrasi
Oleh I Ketut Puspa Adnyana
Om Swastyastu
“Sujud hamba kepada Hyang Paramakawi atas kerunia yang melimpah. Doa untuk para leluhur agar tetap damai. Pengampura, dumogi ten keneng pastu, upadrawe”.
“janmana jayate sudrah samskarairdvija ucyate”: semua orang lahir sebagai sudra, melalui diksa/dvijati seseorang menjadi Brahmana.
PENGANTAR
Beberapa puluh tahun lampau seorang kawan bertanya, apa sanksi bagi sulinggih yang melanggar sesane? Saat itu penulis melakukan koordinasi dengan PHDI Pusat dan mendapat jawaban, bahwa perlu ada Kode Etik Sulinggih. Kemudian penulis juga meminta penjelasan Dharma Adyaksa dan dijelaskan bahwa hanya NABE (Nabe Waktra, Nabe Saksi, Nabe Tapak) yang dapat memberikan hukuman kepada sulinggih yang melakukan pelanggaran. Namun ketika akan dilakukan koordinasi dengan NABE TAPAK, sang pandita sudah lebar. Maka tidak ada jawaban yang pasti. Sekarang banyak lagi pertanyaan pertanyaan yang muncul karena adanya kasus kasus baru yang senada dengan apa yang penulis alami. Sesungguhnya pedoman sesane sangat banyak. Ketika ada pelanggaran, tentu saja bersifat spesifik dan kasuistis karakter, sama sekali tidak terkait dengan lembaga kepanditaan yang sangat suci***
SAMSKARA MANUSIA YAJNA
Selama hidup menurut ajaran Hindu sedikitnya ada 16 upacara yang dilakukan terkait dengan diri sendiri. Mulai dari tahap brahmacari (upanayana samskara, wedaharamba samskara, samawartana samskara), tahap grihasta (wiwaha samskara), tahap wanaprastha (wanaprastha samskara) dan tahap terkahir bhiksuka (sanyasa samskara) sampai kepada ngaben (Anjesty samskara).
Namun umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali belum sapai kepada tahap ketiga dan keempat. Tahap ketiga (wanaprastha) dan keempat (bhiksuka) sangatlah berat karena terkait dengan pengontorolan dan pelepasan diri terhadap indera indera. Melapskan diri terhadap ikatan benda duniawi atau badan fisik. Namun sesungguhnya untuk menjadi sukses dalam menjalani hidup pada semua tahapan, pengontrolan indera indera sangat penting (yama-niyama bratha).
Salah satu upacara yang hanya dilaksanakan oleh beberapa orang terkait dengan tahap hidup adalah diksa (upacara dari ekajati ke dwijati). Kata Dwijati merupakan kata sanskerta, yaitu: “dvi” dan “jati”. Dvi artinya dua dan jati berasal dari akar kata “Ja” yang artinya Lahir. Arti kata Dwijati yaitu lahir dua kali. Lahir pertama dari seorang ibu dan lahir yang kedua dari guru suci (nabe). Seseorang betapapun pandainya belum dapat disebut dwijati, atau sulinggih (untuk semua sebutan) apabila belum melaksanakan upacara diksa.
Mengenai sebutan (abhiseka) para diksita, sesuai Keputusan Mahasabha PHDI ke-2 tanggal 2 s/d 5 Desember 1968,yaitu: Pedanda, Bhujangga, Rsi, Bhagawan, Mpu, dan Dukuh. Semua bhiseka itu disebut sulinggih. Sulinggih ialah mereka yang telah melaksanakan upacara diksa, ditapak oleh Nabe, yang dipilihnya (ada hubungan rohani, keleteg hati).
Dengan demikian, sulinggih (Brahmana) merupakan strata tertinggi dalam sosial tatanan masyarakat Hindu. Dalam ajaran Weda disebutkan “kebiasan kebiasaan para sulinggih” adalah sumber kebenaran yang kedua setelah Weda, dari kelima sumber kebenaran. Seorang anak wajib menghormati orang tua. Antara ayah dan ibu, penghormatan kepada ibu 100 kali dari ayah, dan penghormatan kepada guru suci (sulinggih) 200 kali. Seorang raja memberi hormat kepada sulinggih, dan memberikan jalan terlebih dahulu. Demikian tingginya kedudukan seorang sulinggih menurut ajaran Hindu. Karenanya, tidak ada yang lebih utama dari seorang sulinggih (Brahmana) yang dengan ketat melaksanakan ajaran weda.
DASAR HUKUM (RTA)
Secara umum pelaksanaan diksa telah diatur dalam keputusan PHDI, berbagai lontar yang sangat banyak jenisnya, antara lain lontar lontar: Siwa Sasana, Widhipapincatan, Krama Mediksa, Kramananing Dadi Wiku, Silakrama, Ekapratama, Wertisasana, Wrahaspatittava, dan lainnya. PHDI mulai dari desa sampai ke tingkat provinsi diwajibkan melakukan diksa pariksa terhadap calon diksita. Karena itu, secara administrasi memenuhi syarat formal. Secara batiniah terkait dengan penabean.
Dalam pustaka suci Weda sebagai dasar hukum, yang tentu saja diacu dalam lontar lontar tersebut, diksa dijelaskan dengan terang. Dalam Atharvaveda XI.I.I. dapat ditemui mantram yang berbunyi : ”Satyam Brhad Rtam Ugram Diksa Tapo Brahman Yajña Prithiwim Darayanti”.
Artinya : “Sesungguhnya satya Rta Diksa Tapa Brahman dan Yajña, yang menyangga dunia ini.”
Dalam pustaka suci Yajurveda XIX. 36, disebutkan: ” Vretena diksam apnoti, diksayapnoti daksinam, daksinam sraddham apnoti sraddhaya satyam apyate “
Artinya: “Dengan melaksanakan brata, seseorang mencapai diksa, dengan diksa seseorang memperoleh daksina dan dengan daksina seseorang mencapai sraddha, melalui sraddha seseorang mencapai satya”.
Menurut pustaka suci Atahrvaveda dan Yayurveda kedudukan hukum diksa menentukan kelangsungan hidup alam semesta. Karena tugas para dwijati yang lahir dari upacara diksa adalah untuk mempelajari weda dan mengajarkan weda kepada umat manusia.
Bhagawad Gita IV.19 menyebutkan: “yasya sarve samarambhah, kama samkalpa varjitah, jnanagni dagdha karmanam, tam ahuh panditam budhah”
Artinya: “yang bekerja tanpa nafsu dan motif, kerjanya dibakar api ilmu pengetahuan, dinamakan orang-orang arif, sebagai seorang sulinggih budiman”.
Dalam Manawa Dharma Sastra II.167, disebutkan: A hiawa sa nakhagrebhyah param tapyate tapah, yah sragwyapi dwijo dhitw, swadhyayamcaktito nwakam”.
Artinya: “Sesungguhnya orang dwijati itu melakukan tapa brata yang tertinggi, walupun memakai kalung bunga sampai keujung jarinya, jika setiap harinya mengucapkan weda di tempat sepi dengan sungguh sungguh dengan seluruh kemampuannya.
Baik pustaka suci Sruthi (Weda, didengar) dan Smerthi (Dharmasastra, diingat) maupun lontar lontar yang merupakan penjabaran ajaran Weda lebih lanjut dengan tegas mensyaratkan dan karakter seorang sulinggih yang sangat utama. Karena itu, tidak ada celah bagi umat untuk menyalahkan seorang Sulinggih.
PELANGGARAN SESANA
Sulinggih adalah rohaniawan Hindu atau seorang Guru Suci, yang telah mengabdikan diri pada pelayanan dan pengajaran kepada umat berdasarkan ajaran Weda (sevanam, dharsyam). Namun demikian dalam fakta kehidupan sebagai mahluk sosial yang masih terbentuk dari darah dan daging, kadangkala dalam jumlah yang sangat sedikit terjadi pelanggaran sesana. Pelanggaran sesane ini juga sudah dijelaskan dalam pustaka pustaka yang telah disebutkan.
Selanjutnya Manawa Dharma Sastra II 168, disebutkan: ”yo nadhityo dwijo wedam anyatra kurute cranam, sanjiwanewa cudratwam acu gacchati sanwayah”.
Artinya: “ Seorang dwijati yang tdaik mempelajari Weda, tetapi mempelajari hal hal lain cepat akan jatuh, walaupun semasih hidupnya, hingga pada kedudukan seorang Sudra sampai pada keturunannya”.
Sebagaimana sukta tersebut, seorang brahmana (dwijati) yang melakukan pelanggaran akan jatuh tujuh terunan kebawah dan menarik leluhurnya tujuh tingkat ke bawah. Demikian juga apabila seorang brahmana terus mampu meningkatkan kualitas dirinya tekun mempelajari weda akan dapat mengangkat dan mendorong trah keturunnya ke tujuh tingkat lebih tinggi.
Dalam Manawa Dharma Sastra III.15, disebukan: ”Hinajati striyam mohad udwa hanto dwijatayah, kulanyewa nayantuaacu sasamtanani cudratam”
Artinya: Orang dwijati yang karena kebodohannya kawin dengan wanita sudra akan cepat menjatuhkan (martabat) keluarganya dan anak anak mereka ke tingkat sudra”.
Selanjutnya Manawa Dharma Sastra III.17, disebutkan: “Cudram cayanamaropya Brahmano yatyadhogaatim, janayitwa sutam tasyam brahmanyadewa hiyate”.
Artinya: “Seorang Brahmana yang membawa wanita sudra ke tempat tidurnya, setelah meninggal akan jatuh ke neraka, kalau ia berputera daripadanya, ia akan kehilangan tingkat kebrahmanaannya”.
Kedua sukta dalam Manawa Dharma Sastra tersebut dengan jelas menyabutkan akibat dari pelanggaran sesana, yang berakibat bukan saja pada sang dwijati tetapi juga ketunan dan trahnya.
PERLUKAH KODE ETIK LAGI?
Jelas bahwa dwijati (barhamana) yang melakukan pelanggaran terhadap “sesane” disamping secara sosial dalam masyarakat mendapat hukuman etika tetapi juga tidak boleh ditunjuk lagi dalam melaksanakan upacara (muput karya, nglokapalasrya). Karena akan mengakibatkan baik yang muput ataupun umat akan mengalami karma buruk, sebagaimna disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra. Dengan memahami “batasan” seorang sulinggih seharusnya tidak terjadi pelanggaran. Namun dapat dimaklumi bahwa selama badan fisik diselimuti triguna, kesalahan tempatnya pada manusia.
Sekarang ini adalah zaman kaliyuga, yang mana 75% perbuatan adharma yang berkuasa dan hanya 25% yang masih menegakkan dharma. Karena pedoman pedoman dalam Weda dan Dharmasastra, demikian juga pada lontar lontar sebagai turunan weda, sudah jelas.
Pertanyaan besarnya: Apakah masih diperlukan KODE ETIK SULINGGIH? Siapa yang menyusun drafnya, Sabha Walaka atau Sabha Pandita? Lalu lembaga apa yang memutuskannya. Sedangkan tugas PHDI adalah dalam memutuskan keragu-raguan dalam bhasya ajaran Weda (Manawa Dharma Sastra XII.110-114). Apakah prilaku menyimpang dari sulinggih ini merupakan ranah PHDI? Mungkin perlu dirumuskan dalam Mahasabha yang akan datang.
Semoga semua mahluk berbahagia.
Om santih santih santih Om



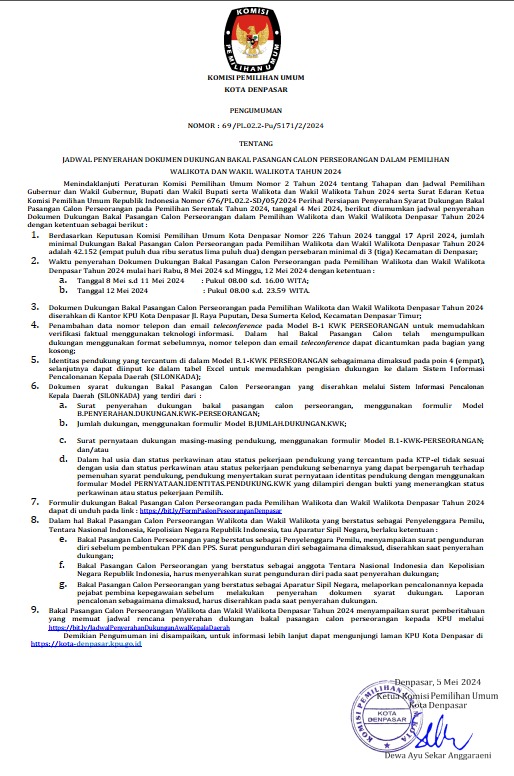









Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.