Kenapa tak Ada Demo Kenaikan Sembako?
Oleh: Komang Suarsana
DEGUP jantung rakyat Indonesia sempat mengencang, menjelang 30 Maret 2012 lalu. Dalam wacana sebelumnya, rakyat sudah diajak bersiap-siap menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 1.500. Dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.000/liter. Rencananya kenaikan itu diberlakukan pemerintah per 1 April.
Denyut jantung makin kencang ketika pada detik-detik menjelang berakhirnya bulan Maret, sejumlah kekuatan politik masih menunjukkan sikap mendukung kenaikan harga. Hanya satu-dua parpol yang menolak.
Akhirnya, setelah berlangsung rapat paripurna hingga dinihari tanggal 31 Maret, DPR-RI sepakat menunda rencana menaikkan harga BBM pada 1 April 2012. Meskipun hasil rapat menyepakati penundaan kenaikan BBM dan menahannya hingga harga ICP melebihi 15 persen dalam enam bulan, keputusan itu terbilang rancu.
DPR sejatinya bukan menolak kenaikan harga BBM. Sidang paripurna hanya menyetujui adanya penambahan Ayat 6a yang menyatakan bahwa “pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan”. Keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 7 Ayat 6 yang isinya menyebutkan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
BBM vs Sembako
Keputusan DPR-RI menunda kenaikan harga BBM memang disambut gembira sesaat. Khususnya oleh rakyat kebanyakan yang hanya terfokus perhatiannya ke harga BBM semata. Di lain sisi, imbas dari rencana kenaikan harganya malah sudah didahului oleh kenaikan harga sembako di tengah-tengah masyarakat.
Kemarin saya mendengarkan cerita seorang ibu yang mengeluhkan harga sembako pada naik semua. Harga gula pasir yang awalnya hanya Rp 11 ribu sekarang menjadi Rp 12 per kilogramnya, minyak goreng menjadi Rp 11.500 sebelumnya hanya Rp 10.500 per kilogramnya. Ternyata sembako yang lain juga mengalami hal yang serupa dan kisaran kenaikan harganya mencapai Rp 1.000.
Sungguh ironis, di tengah perekonomian rakyat yang rendah, pemerintah mau tak mau menaikkan harga BBM dan hal ini pun langsung berimbas kemana-mana. Harga minyak dunia yang terus melambung membuat negara kita kewalahan. Jika subsidi BBM tak dipangkas, justru akan membebani anggaran negara dan ujung-ujungnya membuat perekonomian nasional terseok-seok.
Entah ini sebagai dinamika, pergeseran, evolusi, atau malah anomali, namun jika diingat bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat dari mulai primer, skunder, dan tersier, tampaknya reaksi sebagian kita pada kenaikan harga BBM itu kurang proporsional. Benar bahwa di era produksi dan industri ini, BBM adalah unsur primer. Tetapi, masih kalah primer dibanding sembako.
Secara ilmiah, mengonsumsi sembako adalah ciri utama makhluk hidup. Tak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan makanan. Sedangkan BBM, ia mulai menempati posisi penting sejak era industrialisasi yang secara masif dimulai pasca-Perang Dunia II.
Rencana dan kenaikan harga BBM dipastikan diikuti, dibarengi, bahkan didahului oleh kenaikan harga sembako. Di sinilah ketidakproporsionalan reaksi kita semakin tampak, yaitu reaksi yang tidak direlevansikan dengan tingkat kebutuhan itu sendiri apakah sangat primer atau sekadar primer.
Terhadap harga sembako yang konsumsinya merata dan berhubungan langsung dengan nyawa manusia, kenaikan harga mendapat pemakluman sebagai dinamika atau hasil dari mekanisme pasar. Sedangkan terhadap harga BBM, reaksi masif dan kadang kasar itu seolah ingin menunjukkan kita akan lebih susah tanpa BBM dibanding tanpa sembako.
Tak ada demonstrasi seberani apalagi anarkis ketika memperjuangkan harga sembako yang terjangkau pada tingkat konsumen dan menyejahterakan di tingkat petani. Petani kita hidup miskin, tak banyak yang begitu peduli. Kita membeli beras yang mahal, bukankah saya bisa puasa? Tapi jangan coba harga BBM dinaikkan, kita siap mengerahkan semua sumber daya massa untuk turun ke jalan. Dampak sosial kenaikan harga BBM jauh lebih kompleks dibanding dampak sosial harga sembako.
Atas BBM dan sembako, negara kita punya otoritas atau instrumen yang mengendalikan pengadaan, harga, distribusi, dan sebagainya. Harga beras misalnya, ada raskin atau operasi pasar. Harga ini tidak sepenuhnya dilepas ke mekanisme pasar sebagaimana komoditas lain seperti material bangunan. Pertanyaannya, bukankah seharusnya unjuk rasa itu disatupaketkan antara BBM dan sembako?
Lalu, mengapa tidak ada reaksi masif ketika petani tanpa lahan atau petani kecil sama sulitnya dengan kosumen? Mengapa kita tidak merasa terpanggil ketika melihat otoritas yang mengurus pangan tidak sesibuk otoritas pengurus energi padahal keduanya sama-sama naik harga?
Sebagai sebuah ilustrasi: Dari sisi kuantitas, 1 liter bensin katakanlah sama dengan 1 kg beras. Namun dari sisi harga, harga 1 kg beras non-raskin dipastikan jauh di atas 1 liter bensin, apalagi setelah kenaikan harga. Dari sisi kebutuhan pun, jelas bensin masih kalah primer dibanding beras. Lalu, mengapa reaksi kita atas kenaikan harga tidak relevan jika dibandingkan posisi kedua kebutuhan tersebut dalam menunjang kehidupan kita?
Ciptaan Tuhan
Tidak salah sama sekali menentang kenaikan harga BBM. Sama sekali tidak salah. Tanpa BBM, dipastikan semua mesin yang menjadi alat bantu kehidupan manusia itu akan berhenti. Maka, adalah logis jika menunjukkan reaksi yang masif ketika harga BBM itu dinaikkan.
Tapi dengan satu catatan bahwa reaksi masif itu akan tetap logis apabila kita mampu menunjukkan reaksi yang sama masif ketika perut kita terancam secara langsung oleh kenaikan harga pangan. Sebab, mesin adalah ciptaan manusia, sedangkan manusia adalah ciptaan Tuhan.
Artinya, kalau kita menunjukkan reaksi lebih masif atas kenaikan harga BBM dibanding kenaikan harga sembako, bukankah logis juga jika dikatakan bahwa dalam pandangan kita mesin yang merupakan ciptaan manusia itu lebih penting dibanding perut kita yang merupakan ciptaan Tuhan?
Dari sekian banyak demonstrasi, terlihat bahwa kadar demonstrasi atas kenaikan harga BBM adalah yang tertinggi dibanding kadar demonstrasi di bidang lain, seperti pendidikan, hukum, atau pertanian. Di atas kadar itu, mungkin tidak bisa lagi disebut demonstrasi, tetapi reformasi atau malah revolusi. Pada sisi yang lain, hanya gara-gara minyak naik saja, tak mungkin kita sampai melakukan reformasi apalagi-lah revolusi. Lalu, bagaimana cara kita menomorsatukan Tuhan kalau ternyata demonstrasi kadar tertinggi ditujukan bukan untuk perut dan nyawa manusia, tetapi untuk tetap berjalannya alat-alat bantu manusia seperti mesin itu?
Kita bertanya: mengapa reaksi terbesar ditujukan bukan pada harga sembako yang mahal yang bisa mengancam perut manusia, tetapi pada harga BBM yang sebenarnya masih kalah penting dibanding sembako? Tak ada kegaduhan sangat serius ketika membicarakan nasib petani atau nelayan. Tapi kalau sudah soal harga BBM, nyawa melayang pun sudah sering terdengar.
Seharusnya ada kadar yang proporsional ketika bereaksi atas fenomena atau dinamika. Pada dasarnya, semua itu ciptaan Tuhan. Tetapi, Tuhan sendiri menglasifikasikan makhluknya di mana manusia ditempatkan di posisi teratas. Lalu, mengapa kita memutarbalikkannya dimana demonstrasi kita atas harga sembako yang berkaitan langsung dengan nyawa itu tak sesemarak demonstrasi harga BBM?
Bukanlah maksud kita memrovokasi kita agar berdemonstrasi yang lebih keras atas kenaikan harga pangan. Kurangilah kualitas dan kuantitas demonstrasi atas kenaikan harga BBM. Lalu, berilah perhatian yang lebih pada harga sembako yang memang merupakan kebutuhan sangat primer itu. Dengan begitu, kita tidak menomorduakan ciptaan Tuhan karena lebih mementingkan “makanan” mesin yang merupakan ciptaan manusia itu dibanding makanan manusia sendiri yang merupakan ciptaan langsung oleh Tuhan itu.
Akan lebih bijak jika demonstrasi atas kenaikan BBM itu dibatasi kualitas dan kuantitasnya di bawah reaksi kita atas harga sembako sembari meningkatkan penghematan atas penggunaan energi. Kalau urusan perut saja pun bisa dihemat, bukankah demikian menyangkut energi tak terbarukan?
Benar bahwa produk-produk pangan itu tak memenuhi salah satu hukum permintaan pasar. Hukum permintaan pasar mengatakan bahwa kenaikan pendapatan konsumen bertendensi meningkatkan permintaan konsumen akan barang atau jasa.
Tetapi, hukum ini tidak berlaku untuk produk pangan. Anda masih miskin atau sudah kaya, tetap saja kemampuan anda makan nasi tidak berbeda jauh. Malah, peningkatan kekayaan itu bertendensi meningkatkan permintaan akan BBM misalnya.
Menurut ilmu ekonomi, begitulah pola sebab akibat mengapa negara agraris cenderung menjadi negara miskin, sedangkan negara industri menjadi negara kaya. Artinya, bahan pangan itu masih kalah populer dibanding energi.
Namun jangan lupa dengan logika sederhana ini : bahwa kita masih dapat hidup tanpa BBM, tetapi mustahil bisa hidup tanpa makanan. Masih banyak harapan untuk menemukan energi alternatif agar mesin-mesin tetap dapat beroperasi. Sejak zaman batu hingga zaman nuklir ini, adakah energi alternatif untuk perut manusia kecuali makanan?
Sekali lagi, demo menentang kenaikan harga BBM tidaklah salah. Akan menjadi lebih benar dan lebih baik lagi, kalau demo itu juga sekarang bias diaktualisasikan dalam bentuk lain, agar rakyat yang menghadapi kenaikan harga sembako tak lagi menjerit.
Penulis, wartawan senior, pemerhati masalah sosial kemasyarakatan.



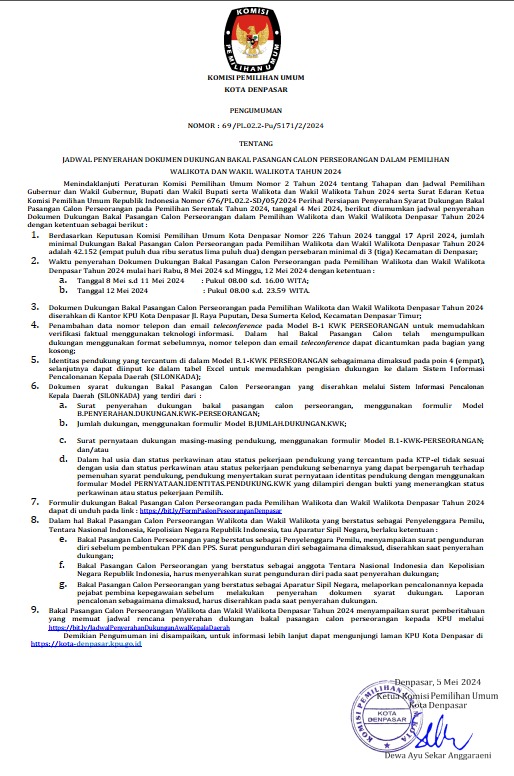









1 Komentar
Mengapa kenaikan Sembako tidak ada yg demo, karena kenaikan itu di sebabkan oleh hukum pasar murni. Dan lebih menjawab rasa keadilan masyarakat. (Artinya situasi pasar yg berdampak politik).
Sedangkan naik turunnya harga BBM lebih disebabkan oleh keputusan politik yang dapat mempengaruhi pasar. Bahkan keputusan politik itu “dicurigai ” bisa mendapatkan “bonus politik dan bunus rejeki” sebagai modal awal untuk mempengaruhi politik kekuasaan berikutnya.