Bali Raksasa Ekonomi Budaya ?
BUDAYA merupakan aset paling strategis bagi pergulatan ekonomi negeri ini, termasuk Bali yang identik dengan sebutan pulau surga para turistik baik domestik maupun manca negara. Terlebih lagi, Bali kini telah disebut sebagai raksasa ekonomi budaya berbasis kearifan lokal dengan tradisi budaya spiritual religius dalam tatanan nilai adiluhung ajaran Hindu yang mendunia dan telah menyejarah selama berabad-abad dalam lingkaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat di tengah peradaban global industri pariwisata dunia.
Kini, perjuangan strategis ekonomi Bali yang menggeliat terus bertumbuh dan berkembang melalui aktivitas industri pariwisata budaya, seperti perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan mengalami ancaman cukup serius dari keindahan perilaku para elite penguasa pemangku kebijakan yang berafiliasi dengan para investor baik lokal, nasional maupun asing. Kenapa ? Karena, pilar utama konstruksi ekonomi budaya tidak dibangun dari kekuatan sektor primer ataupun sekunder, melainkan tergantung kepada sektor tersier (jasa) semata.
Terlebih lagi, para elite penguasa pemangku kebijakan selama ini telah dicap publik terlanjur terkoptasi keindahan perilaku korupsi yang jauh dari akal sehat, serta sangat masif dan bahkan secara koruptif acapkali memanfaatkan relasi kuasa atau jabatannya melalui beragam proyek pro-rakyat untuk memenuhi kepuasan nafsu duniawi kepentingan pribadi maupun kelompok ataupun golongan tertentu. Dalam konteks ini berarti implementasi empat pilar kebangsaan yang secara intensif diwacanakan oleh mendiang Taufik Kiemas selama ini rupanya belum mampu menumbuhkan sikap toleran dalam kehidupan berbangsa, dan bernegera serta bermasyarakat.
Implikasinya, korupsi pun kini telah menjelma menjadi produk budaya dan koruptor dianggap sebagai profesi andalan terbarukan yang sangat menggiurkan dan menjanjikan untuk meraih kekayaan secara cepat dan nyaman. Selain itu, lingkungan kehidupan masyarakat Bali sontak mengalami degradasi moral karena tidak dibangun dengan nilai dan makna, tapi sekadar hidup atas dasar kepuasan nafsu duniawi semata yang berorientasi finansialitas.
Dalam grafik pertumbuhan ekonomi Bali memang cukup tinggi dan bahkan dapat dianggap mampu mendorong upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Tapi, sayangnya pertumbuhan ekonomi Bali yang cenderung telah melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional ini justru berdampak negatif bagi denyut nadi kehidupan budaya di tengah kehidupan masyarakat kekinian ataupun masa mendatang. Kenapa ? Karena, kesenjangan sosial terkait ketimpangan kesejahteraan masyarakat Bali cenderung semakin tinggi dan cukup memprihatinkan.
Pergulatan ekonomi budaya dalam personalitas kepentingan tanpa solusi kreatif yang berkeadilan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat secara universal dapat dipastikan akan tumbuh menjadi raksasa ekonomi budaya yang menciptakan kebangkrutan sosial secara berkelanjutan dari beragam sektor kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Proses demokrasi pun akan mengalami degradasi moralitas dan inharmoni karena termarjinalisasi keindahan perilaku dari praktik mafia premanisme budaya. Dalam konteks ini, proses menjalankan kebebasan yang dikonstruksi melalui relasi kuasa atau jabatan para elite politik penguasa pemangku kebijakan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa pakraman termasuk lingkungan banjar/dusun secara lintas generasi telah melampaui batas kewajaran dan bahkan cenderung kebablasan.
Jika fenomena ini dibiarkan berlarut-larut tentunya dapat berdampak buruk terhadap upaya pencetakan karakter bangsa melalui politik ekonomi dan budaya dalam ekologi pemerintahan sebagai program jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur pembangunan berbasis lingkungan di tengah kehidupan budaya masyarakat Bali dapat dipastikan akan menjadi semakin karut-marut dan bahkan kehilangan ruh dari taksunya yang telah mendunia dan menyejarah beradab-abad lamanya.
Di samping itu, bahkan diyakini secara perlahan budaya agraris sebagai pohon kehidupan kebudayaan bangsa berbasis kearifan budaya lokal khas Bali akan tinggal kenangan akibat gejolak peradaban zaman globalisasi kekinian. Di mana, Bali yang disebut sebagai pulau seribu Pura, akan menjadi negeri beton dengan gedung bertingkat yang menjulang tinggi ke angkasa dan jalan tol ataupun jalan layang dengan tingkat kemacetan yang sangat krodit dan kompleks, serta kehidupan berbiaya tinggi dengan populasi pengangguran dan kemiskinan yang terus-menerus bertambah secara dramatis.
Budayawan Prof. Dr. I Made Bandem, MA bahkan sempat menegaskan bahwa denyut nadi kehidupan seni budaya Bali tidak dapat dipisahkan dari realitas kreativitas budaya agraris (pertanian) dengan konsep subaknya. Ini karena budaya agraris merupakan spirit dasar dari kebangkitan ekonomi kerakyatan di tengah kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam pergulatan industri pariwisata dunia secara berabad-abad lamanya. Jadi, tidak ada alasan pembenar untuk menghilangkan realitas kreativitas budaya agraris dalam kehidupan seni budaya Bali. Jika itu terjadi berarti budaya yang tumbuh dalam ekonomi global kekinian akan tidak metaksu. Sehingga secara perlahan peradaban budaya Bali termasuk kebudayaan bangsa akan hilang dari kehidupan masyarakat dunia di masa mendatang.
Eksekusi Ketegasan
Menyelaraskan antara kinerja dengan kebijakan memang tidak mudah. Karena membutuhkan kemampuan dalam memformulasikan keunggulan untuk mengeksekusi strategi kebijakan secara tepat waktu agar berdaya guna manfaat secara konkrit dan menyeluruh. Terlebih lagi, dalam praktiknya sikap ketegasan yang terjadi selama ini cenderung masih sebatas kebijakan di atas kertas dalam bentuk beragam peraturan perundang-undangan semata, tapi eksekusi secara konkret di lapangan masih dicap seperti macan ompong ataupun sekadar wacana publik, tanpa adanya aksi konkrit dan signifikan secara nyata di lapangan sesuai kaidah hukum yang berlaku dalam asas keadilan serta menyejahterakan.
Jika pergulatan dari persoalan remeh-temeh ini sengaja dibiarkan terjadi terus menerus secara masif, kondisi kehidupan masyarakat akan semakin memburuk dan tidak teratur serta tingkat kriminalitas akibat dampak negatif dari kesenjangan sosial terkait kesejahteraan hidup bahkan cenderung semakin meningkat dan membahayakan bagi keamanan dan kenyamanan berbangsa, dan bernegara serta bermasyarakat. Selain itu, ekologi pemerintahan dalam menjalankan fungsi pengayoman kepada khalayak publik bahkan terancam bisa mengalami kebangkrutan, karena terjadinya konflik kesenjangan sosial secara sistemik seperti dialami oleh Detroit, kota terbesar di Amerika Serikat, yang dengan terpaksa harus mengajukan perlindungan kebangkrutan (Kompas, 2013/07/20).
Menyikapi hal tersebut sudah semestinya para elite politik penguasa pemangku kebijakan untuk mengedepankan landasan berpikir kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BhinnekaTunggal Ika dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara yang bijaksana, profesional dan berjiwa besar. Dalam konteks ini, berarti para elite politik pemangku kebijakan (pemimpin) dituntut harus mampu mengutamakan kebenaran dan keadilan yang menyejahterakan bagi kepentingan khalayak publik daripada kepentingan pribadi maupun kelompok ataupun golongan tertentu.
Tak hanya itu, publik pun dituntut harus mampu menjadi pengawas dan kontrol sosial terdepan yang paling transparan dan akuntabel, sehingga beragam persoalan remeh-temeh termasuk praktik mafia premanisme budaya yang acapkali terjadi di tengah masyarakat selama ini tidak menjelma menjadi raksasa ekonomi budaya berlabel pro-rakyat. Dengan demikian kehidupan ekonomi budaya yang digagas dalam program pemerintah secara berkelanjutan saat ini maupun masa datang dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta mampu memberikan kesejahteraan sosial secara merata dan berkeadilan.
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dalam acara serimonial penutupan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-35 tahun 2013 ini, tepatnya Sabtu (13/7) di panggung terbuka Ardha Candra, UPT. Taman Budaya (arts centre) Bali, Denpasar bahkan sempat menegaskan bahwa konstruksi budaya dalam PKB sebagai penyangga utama sekaligus pengawal peradaban budaya dari gempuran penetrasi budaya global yang tidak sesuai dengan nilai Satyam (kebenaran), Siwam (kesucian/kemuliaan), Sundaram (keindahan/keharmonisan) yang ada dalam ajaran Hindu sebagai nafas kehidupan kebudayaan bangsa berbasis kearifan lokal khas Bali. Dalam konteks ini berarti denyut nadi kehidupan budaya dituntut harus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga mampu memiliki daya saing global dalam industri pariwisata dunia, demi kehidupan yang lebih baik dan menyejahterakan secara berkelanjutan.
Menyikapi dinamika tersebut, perlu adanya politik budaya yang didasari niat baik dan ketulusan hati berjiwa besar dalam menegakkan supremasi hukum secara tegas dan berkeadilan dengan semangat ngayah tulus iklas tanpa pamrih, demi kebaikan bersama dalam menjaga landasan kebangsaan yang merdeka dan berdaulat di masa mendatang. Sehingga, konstruksi beragam budaya salah kaprah yang cacat moral seperti praktik mafia premanisme budaya dalam kehidupan masyarakat desa pakraman selama ini dapat dituntaskan secara lebih beradab dan bermartabat.
Proyek Kemacetan
Pertumbuhan ekonomi budaya Bali secara perlahan memang telah menciptakan simpul kemacetan yang sangat krodit dan kompleks. Kapasitas ruas jalan raya seakan tidak sebanding dengan populasi penjualan kendaraan bermotor baik roda dua (sepeda motor) maupun roda empat (mobil). Tak pelak, kemacetan pun menjadi budaya yang telah mentradisi dalam kehidupan masyarakat kekinian. Penataan fasilitas publik dengan beragam proyek pun terus menerus dilakukan setiap tahun. Bahkan, seakan menjadi proyek abadi yang menghabiskan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi Bali, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sayangnya, upaya penataan fasilitas publik tersebut tidak disertai dengan keindahan perilaku masyarakat untuk selalu menjaga dan memanfaatkan fasilitas publik tersebut sesuai fungsinya dengan sebagaimana mestinya. Bahkan, secara arogan para kelompok internal dalam desa pakraman acapkali melakukan tindakan tidak terpuji dan cacat moral terhadap kemanfaatan dari fasilitas publik tersebut. Di antaranya sebagai lahan parkir liar, garase kendaraan, hingga usaha bisnis/berdagang dan parkir reguler atas dalih keagamaan. Akibatnya, praktik mafia premanisme budaya pun menjadi semakin merajarela. Kenapa ? Karena tidak adanya tindakan tegas dari para elite politik penguasa pemangku kebijakan dalam hal ini instansi terkait di bidangnya untuk menertibkan ataupun menindak secara tegas keindahan perilaku dari kenyamanan tak bermartabat tersebut sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu demi kebenaran dan keadilan bagi kepentingan khalayak publik, masyarakat dalam arti seluas-luasnya.
Di samping itu, upaya untuk mengatasi kemacetan pun tidak pernah tuntas dan bahkan cenderung semakin memprihatinkan. Sehingga segala program pembenahan yang dilakukan pemerintah dengan sistem tambal sulam selama ini acapkali dianggap publik kurang efektif dan bahkan cenderung dicap terkesan sebagai pemborosan dan sekaligus sekadar upaya bagi-bagi proyek anggaran dari APBD maupun APBN secara kolektif, meskipun memang tidak bersifat menyeluruh. Dalam artian, solusi kreatif yang dilakukan selama ini seringkali tidak menyentuh esensi dasar dari pokok permasalahan yang terjadi dan bahkan justru memicu masalah baru yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap upaya peningkatan pelestarian dan pengembangan seni budaya bangsa berbasis kearifan lokal khas Bali secara berkelanjutan. Di mana indikatornya adalah semakin maraknya praktik korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan hingga ekologi masyarakat dalam desa pakraman.
Menyikapi realitas tersebut, para elite politik penguasa pemangku kebijakan dituntut harus mampu saling bersinergi dengan masyarakat di tengah desa pakraman secara holistik dan komprehensif guna menentukan solusi kreatif untuk mengatasi beragam persoalan bangsa. Sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam menjalankan tugas pengabdian dan pengayoman bagi kepentingan khalayak publik sesuai landasan pemikiran kritis dari empat pilar kebangsaan.
Tak hanya itu, para pelaku bisnis dalam sosial media pun dituntut harus aktif dan mampu tampil terdepan dengan sikap kritisnya melalui loyalitas dari jurnalisme fakta dan makna yang lebih mengutamakan idelogi kebebasan pers dengan kredibilitas, serta independensi dan netralitasnya dalam menyampaikan informasi jurnalistik kepada khalayak publik, sehingga mampu membangun opini publik yang akurat dan mencerahkan, demi Bali tercinta yang telah mendunia dengan pariwisata budayanya.
Ketua Majelis Pertimbangan Kebudayaan (Listibya) Bali, I Gusti Putu Rai Andayana bahkan sempat menegaskan bahwa segala persoalan remeh-temeh yang terjadi selama ini termasuk proyek kemacetan yang semakin memprihatinkan dan mengkhawatirkan hanya dapat diatasi secara tuntas oleh para elite politik penguasa pemangku kebijakan (pemimpin) yang selalu setia memegang teguh filsafat kehidupan berlandaskan ajaran Hindu, yakni ngayah tulus iklas tanpa pamrih dengan sikap berjiwa besar sekaligus arif dan bijaksana dengan niat baik dan ketulusan mengabdi untuk kebenaran dan keadilan bagi kepentingan khalayak publik. Artinya, mampu bersikap tegas tanpa harus terkoptasi kapitalisme global dari hegemoni keindahan perilaku kelompok internal dalam desa pakraman yang selama ini telah dicap publik sebagai otak atau aktor utama dari proses genosida atau penghancuran budaya Bali secara masif. WB-MB



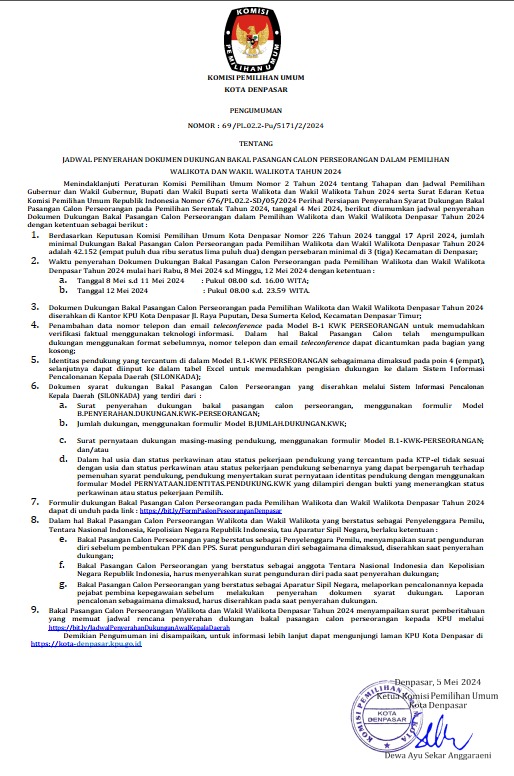









3 Komentar
Pola pembangunan Bali semakin meniru pola pembangunan di tempat-tempat lain di Pulau Jawa, padahal Bali memiliki keunikan. Bali berbeda dengan Jawa. Kedua, ada banyak kegagalan di Pulau Jawa yang diulang di Bali. Salah satunya yang paling nyata, mengurai kemacetan dengan membangun Jalan Tol. Sudah terbukti jalan tol yang bergelayutan di Jakarta bukan mengurai kemacetan tetapi menambah volume kendaraan. Ide pembangunan 6 ruas jalan tol di Jakarta nyata-nyata ditolak masyarakat Jakarta. Sungguh aneh, Bali justru hendak mengulangi kesalahan ini. Dari penelusuran sekitar jalan tol, simpang siur dan underpass, titik-titik kemacetan di masa depan sudah dapat diprediksi.
Hal Kedua, pemerintah propinsi belum melakukan penegakan hukum efektif. Paling nyata, bagaimana menyelesaikan pembangunan pulau serangan yang mangkrak. Siapa harus bertanggung jawab? Kemanaka investor itu?
Pengulangan kegagalan pembangunan di Jawa plus keteledoran untuk melakukan penegakan hukum itu terus dipelihara. Bali memiliki manusia berkualitas, berkebudayaan, berintegritas tinggi. Yang diperlukan adalah manusia-manusia semacam ini mengambil peran di segala titik penting bagi kedaulatan Bali.
Bali memang berbeda dengan Jawa dan Bali memiliki keunikan yang tidak bisa membuat jalan layang disepanjang daratan untuk mengantisipasi kemacetan karena budaya dan adat Bali rentan dengan kesakralannya, apa lternatif lainnya ? dan kegagalan sebuah tujuan Pemangunan pada hakekatnya terletak pada perlakuan yang sesunggungnya, sukseme.
Ane tiwas tileh je nu liu…..ane beduur ape seng tolihe