Nasionalisasi Kata Spesifik
Jakarta (Metrobali.com)-
Setiap bahasa selalu mempunyai khazanah kosa kata yang bermakna amat spesifik sehingga sulit ditemukan padanannya pada kosa kata dalam bahasa lain.
Begitu juga dengan bahasa Jawa yang mempunyai kosa kata spesifik yang tak mudah ditemukan sinonimnya pada bahasa Indonesia.
Untuk memperkaya bahasa Indonesia, tak kelirulah jika kata-kata bermakna spesifik itu dinasionalisasi ke bahasa Indonesia. Menasionalkan kata-kata daerah tak semata berlaku untuk bahasa Jawa, tentu saja.
Dalam konteks bahasa Jawa, ada kata yang layak dijadikan warga bahasa Indonesia sehubungan dengan terpilihnya Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi.
Kata bahasa Jawa ini sangat dikenal luas dan dimengerti oleh orang Jawa yang bertutur bahasa Jawa, baik yang ragam halus ataupun kasar. Namun kata dalam bahasa Jawa ini punya fitur semantik kasar, tak bermartabat dan memalukan. “Ndermis”, itulah kata yang diusulkann di sini untuk menjadi kosa kata bahasa Indonesia.
Nasionalisasi “ndermis” di sini dikaitkan dengan konteks politik nasional. Ya, sebentar lagi Jokowi menyusun kabinet. Dia tentulah berpikir keras tentang siapa memimpin kementerian apa. Pasti ada sekian banyak orang di lingkarannya yang bermental luhur, yang selama ini menyokongnya sehingga wong Solo ini terpilih menjadi presiden. Mereka ini tulus. Tak meminta imbalan dalam bentuk jabatan atau proyek. Di antara yang bermental luhur itu, pasti ada sekian yang berjiwa agung. Mereka ini lebih dari sekadar tulus. Bahkan karena begitu tulus, mereka memutuskan segera menghilang, menjauh dari lingkaran dekat Pak Presiden. Menyepi, mengosongkan diri dari pamrih.
Nah, di sekitar Jokowi sangat mungkin juga ada orang-orang yang merasa telah berjasa dan merasa pantas mendapat imbalan, apa pun wujudnya. Mereka ini bisa dibagi dalam dua kelompok. Pertama, orang-orang yang dengan malu-malu menunggu, berharap dalam diam, moga-moga Jokowi berbelas kasih pada mereka dengan memberikan imbalan atas kerja mereka selama menjadi tim sukses. Kedua, orang-orang yang tanpa malu-malu merengek meminta-minta jabatan atau proyek atau apa pun sebagai balas budi atas jerih payah mereka dalam memenangkannya melawan Prabowo. Mereka inilah orang-orang yang bermental “ndermis”.
Ajektiva Jawa ini biasa dilontarkan para orang tua pada anak-anak mereka yang getol meminta pantang surut sebelum permintaan mereka dikabulkan. Karena kesal mendengar rengekan yang tak berkesudahan, sang orang tua pun mencela: “Bocah kok ndermis!” Kata-kata menyakitkan ini ampuh menghentikan rengekan anak. Hanya anak yang “ndermis” sejatilah yang tak terpengaruh oleh cacian menghina merendahkan itu.
Alangkah jauh lebih nista jika watak “ndermis” yang mestinya hanya pantas dikandung anak-anak itu dimiliki orang-orang dewasa, apalagi yang berkesempatan hidup di lingkaran elit politik.
Saya ingin Jokowi menggaungkan kata sifat Jawa ini untuk mencela –siapa pun yang berwatak meminta-minta– dalam ajang revolusi mental senyampang mengangkat status lokal ajektiva itu ke taraf nasional karena kandungan maknanya yang khas dan tak terpadani oleh ajektiva Indonesia. “Ndermis” pun kelak berubah jadi ndermis, tanpa tanda kutip maupun ditulis dalam huruf miring. Tapi, eh, tunggu dulu. Gugus konsonan “nd-” di awal kata Indonesia agaknya tak lazim. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cuma memasukkan satu lema “ndoro” ‘kata sapaan kepada orang bangsawan atau majikan’ dan turunannya “ndoroisme” `kepatuhan’; `ketaatan’; `bersikap tunduk’.
Bila “ndoro” dan “ndoroisme” dijadikan dasar analogi untuk memasukkan “ndermis” sebagai warga bahasa Indonesia, masalahnya selesai. Namun, disimak dari aspek pembentukan kata, soalnya tak sesederhana itu. Gugus konsonan “nd-” di awal kata dalam “ndermis” tak bisa disamakan dengan proses pembentukan gugus konsonan “ng/ny” pada “ngopi/nyate” yang masuk dalam bahasa Indonesia ragam cakapan.
Sebagai hasil penambahan morfem {n} pada kata dasar berhuruf awal {d}, gugus konsonan “nd-” tak mudah ditemukan dalam bahasa Indonesia ragam cakapan sekalipun. Kalau toh suatu saat gugus konsonan seperti itu ditemukan, “ndermis” tak serta merta bisa diterima sebagai bahasa Indonesia sebab tak ada kata dasar “dermis” yang menurunkan “ndermis”.
Proses linguistik yang biasa disebut simulfiks, yakni penambahan bentuk terikat yang bukan merupakan suku kata pada kata dasar, dalam bahasa Indonesia, selama ini juga hanya menyebabkan kata-kata itu berposisi sebagai bahasa cakapan dan bukan bahasa Indonesia standar atau baku.
Dengan demikian nasionalisasi “ndermis” akan menghadapi kendala bentuk. Tapi kendala ini bisa diterobos jika preseden “ngabuburit” yang juga merupakan bahasa Sunda bisa diterima sebagai warga bahasa Indonesia.
Kata “ndermis” barangkali akan sulit diterima dalam khazanah bahasa Indonesia antara lain karena fitur semantik yang dikandungnya tak mendukung bagi upaya pembangunan karakter agung mulia.
Namun, jika sudut pandang yang dipakai adalah bahwa dengan nasionalisasi “ndermis” untuk membuat malu mereka yang bermental peminta-minta, nasionalisasi “ndermis” bisa dimungkinkan.
Dalam perjalanan bahasa-bahasa daerah yang menjadi bahasa nasional, ada kisah sukses dan kisah gagal. Beberapa yang dinilai berhasil adalah “legawa”, “lengser”. Yang gagal antara lain: “mangkus” dan “sangkil”. Kata-kata seperti “padika” yang diusulkn mendiang Sudjoko untuk menggantikan “metode”, dan “kepros” untuk “objektif” juga kurang mendapat sambutan.
Penentu sukses atau gagalnya bahasa daerah yang naik derajat menjadi warga bahasa Indonesia adalah masyarakat, masyarakat yang bertutur dalam bahasa Indonesia. Apakah “ndermis” akan berterima, waktu lah yang membuktikan. AN-MB




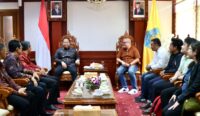






Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.