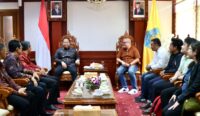Tahun Baru Caka 1946, Jebakan Melemahnya: Keimanan dan Memudarnya “Manik” dan “Taksu” Keagamaan
Denpasar, (Metrobali.com)
Dalam agama dengan pesan “langit”, insan-insan manusia diajarkan, disadarkan dan bahkan “dipaksa” untuk mengembangkan diri mengikuti sifat-sifat Tuhan, dengan seluruh persyaratannya, yang diharapkan mampu mencapai kebebasan spiritual, moksha, di sini, di dunia yang maya ini. Tetapi realitasnya “jauh panggang dari api”, wacana tentang sifat-sifat Tuhan terus diwacanakan tetapi realitasnya “penunggalan bayu, sabda, idep” jauh dari itu. Yang banyak terjadi, keakuan dilipat gandakan, keserakahan dirayakan, sikap hedonistik dipamerkan.
Berbeda dengan agama lokal, mendidik, mencontohkan manusia untuk memperbaiki kualitas dirinya, di tengah keterbatasan manusiawi yang ada, melalui lakunya, tanpa terlalu banyak mewacanakan diskursus tingkat tinggi tentang teologi dan filsafat Ketuhanan.
Dalam dikotomi agama seperti di atas, ada kecenderungan perilaku dalam agama sosial menjadi sebuah “industri”, lengkap dengan relasi biaya – manfaat, sehingga akan lahir fenomena sosial: melemahnya keimanan, merosotnya karakter diri, dan kemudian terjebak ke kehidupan yang “serba boleh” berbasis kepentingan, kedangkalan pemikiran dan tuna refleksi diri. Ironi dan tragisnya, di tengah kemerosotan nilai: susila, etika dan moral, wacana tentang: agama, relegiositas dan bahkan spiritualitas semakin “naik daun” di tengah “industri” agama yang hiruk pikuk, yang semakin memudarkan kekuatan transformatifnya, “manik” dan “taksunya”.
Jro Gde Sudibya, intelektual Hindu, penulis buku agama Hindu dan Budaya Bali.