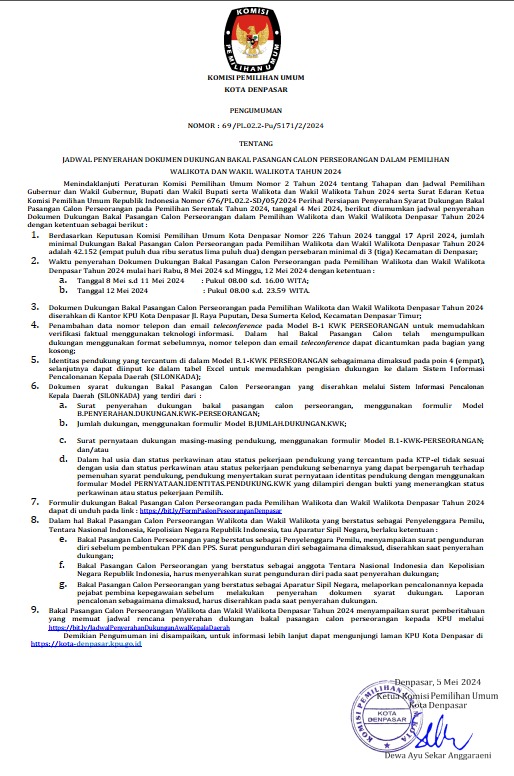Konflik TNI-Polri Kembali Terulang: Urgensi Evaluasi Kebijakan dan Implementasi Reformasi TNI-Polri
Oleh: I Wayan Sudirta
Anggota Komisi III DPR RI (Hukum, HAM, dan Keamanan)
Jakarta (Metrobali.com)-
Untuk kesekian kalinya, ujian terhadap keharmonisan dan kolaborasi hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali terjadi. Pada tanggal 14 April 2024 lalu, konflik TNI-Polri kembali terjadi. Kali ini bentrok terjadi antara anggota TNI AL dan anggota Brimob di Sorong, Papua Barat terjadi. Melalui konferensi pers, Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Johnny Eddison Izir dan Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan menyampaikan permintaan maaf ke publik.
Mereka menjelaskan bahwa konflik tersebut dipicu oleh kesalahpahaman. Saat ini kedua belah pihak sedang melakukan investigasi dan berjanji kepada publik akan menindak tegas para pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.
Menjadi catatan kita bersama, bahwa konflik TNI-Polri ini adalah kejadian berulang di tengah wacana “Sinergisitas TNI-Polri”. Kapolri dan Panglima TNI telah selalu mengikrarkan kebersamaan TNI-Polri yang harmonis dan kolaboratif. Namun apa yang terjadi di lapangan merefleksikan bayangan yang berbeda dari upaya tersebut. Tercatat dari berbagai media bahwa konflik TNI-Polri ini bahkan tiap tahun terjadi, bahkan kejadian serupa telah terjadi pada Maret lalu di bumi Papua yakni bentrok antara TNI-Polri di markas Polres Jayawijaya.
Sebelumnya di tahun 2023, kita juga diingatkan dengan konflik yang terjadi di Makassar dan NTT yang rentang waktunya juga berdekatan. Bahkan selama masa pandemi (2020-2022), dari berbagai laporan seperti Kontras dan Kompas, tercatat terjadi 28 kasus konflik anggota TNI dan Polri. Dalam berbagai laporan tersebut, akar permasalahan adalah kesalahpahaman yang berbuntut pada arogansi dan kekerasan.
Permasalahan Mendasar
Dari berbagai laporan tersebut, saya melihat bahwa konflik TNI dan Polri yang kerap terjadi tersebut merupakan salah satu contoh terjadinya ego-sektoral, dimana semangat dalam organisasi TNI dan Polri yang memiliki jiwa korsa (esprit de corps) yang mengedepankan kesatuan, kekompakan, dan kecintaan terhadap institusi dengan rela berkorban. Implikasinya, bentrok ini menjadi suatu keniscayaan yang tidak akan pernah hilang sepanjang keduanya lebih mengedepankan jiwa korsa dalam arti sempit tersebut. Semangat jiwa korsa seperti Tri Brata dan Catur Prasetya seharusnya dipahami sebagai semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lalu apa saja yang sebenarnya menjadi latar belakang konflik-konflik yang terjadi antara TNI dan Polri selama ini. Saya mencatat bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya atau setidaknya menjadi pemicu perbedaan dan konflik sektoral ini. Pertama, dari sisi kebijakan yakni pengaturan tugas dan kewenangan yang bersinggungan. Banyak aturan yang sebenarnya bertujuan untuk menggabungkan dua kekuatan besar ini dalam menghadapi persoalan tertentu, seperti pengamanan obyek vital, pencegahan dan pemberantasan terorisme, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah.
Hal ini tentu berdampak pada penyediaan sumber daya yang tentu seperti terjadi sebuah “persaingan” atau kompetisi. Gesekan kewenangan dan fungsi ini memang menjadi jawaban kekurangan sumber daya di beberapa sektor atau wilayah, tetapi menjadi sebuah paradoks karena berdampak pada kebersinggungan keduanya di lapangan dan tak heran berbuntut panjang seperti terjadinya konflik dengan kekerasan.
Selanjutnya, terkait dengan tindakan pengawasan dan penegakan aturan. Pelaksanaan sistem pengawasan yang melekat dengan menerapkan prinsip reward and punishment atau meritokrasi yang telah diatur, seharusnya sudah dapat diberlakukan secara konsisten sehingga dapat mencegah dan menimbulkan efek jera.
Banyak pihak sebenarnya mempertanyakan efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan ini, karena seolah budaya kekerasan atau kultur arogansi ini selalu terjadi dan bahkan dikedepankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya hingga dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan etik dan aturan yang ada seolah hanya kepura-puraan atau tindakan formalitas, serta tidak menyasar pada persoalan pokok yang seharusnya menjadi agenda utama dari tujuan pelaksanaan reformasi kultur dan struktur.
Saya juga mencatat adanya sebuah penyederhanaan masalah pada beberapa kasus konflik tersebut. Melihat dari akar permasalahan memang bisa saja terjadi konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau masalah sepele. Akan tetapi hal ini sebenarnya tidak bisa dibiarkan atau ditindaklanjuti dengan mudah atau sepele. Penegakan hukum atau tindakan sesuai aturan seharusnya diberlakukan secara tegas dan konsisten.
Banyak pengamat dan persepsi publik misalnya yang kemudian mempertanyakan transparansi dan keadilan dari beberapa kasus yang terjadi, karena banyak akibat yang terjadi dari konflik tersebut yang melahirkan korban masyarakat dan merugikan masyarakat atau setidaknya meresahkan masyarakat setempat.
Publik seringkali mempertanyakan mengenai tindak lanjut pelanggaran hukum tersebut karena rentan dengan persepsi impunitas dan penanganan secara tertutup atau rahasia oleh keduanya. Masyarakat menilai seharusnya penanganan dan hukuman terhadap anggota TNI-Polri yang melakukan kekerasan, apalagi hingga berdampak pada korban sipil, seharusnya mendapat pemberatan. Status mereka seharusnya dipandang sebagai hal-hal yang memberatkan seperti dalam KUHP yang berlaku bagi masyarakat.
Hal selanjutnya adalah yang terkait dengan kualitas dan integritas yang dibangun dalam sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Banyak anggota TNI dan Polri yang sebenarnya telah dibekali dengan kemampuan rekonsilitatif dan pemahaman untuk mengedepankan kekompakan TNI dan Polri, namun lebih memilih tindakan “anarkis” dalam membela anggotanya dan bahkan berani berjalan di luar nalar atau koridor aturan yang berlaku.
Hal ini tentu menjadi contoh buruk bagi upaya untuk melakukan reformasi dan modernisasi TNI dan Polri yang mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas. Dalam hal ini saya mencatat bahwa sistem kepemimpinan dan pendidikan yang ada pada TNI dan Polri perlu diperbaiki, terutama dalam pemahaman mengenai esprit de corps, akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta menjunjung tinggi etika dan moralitas secara baik dan benar.
Menyikapi Konflik “Ego-Sektoral”
Secara garis besar, saya melihat bahwa persoalan ego-sektoral ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi negara kita yang seharusnya dijawab dengan reformasi kultur dan struktur atau revolusi mental dengan mengedepankan perbaikan mutu pendidikan dan pembangunan integritas SDM. Gesekan antar lembaga atau para pihak dalam menyelenggarakan negara ini, memang sulit untuk dihindari secara penuh dan menyeluruh, apalagi yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat seperti TNI dan Polri, atau instansi terkait lainnya di wilayah-wilayah.
Namun, hal ini terkait dengan bagaimana cara masing-masing pihak dalam memilih untuk mengedepankan rasa tanggung jawab terhadap moralitas dan etika bangsa yang berlandaskan pada filosofi nilai-nilai dalam PANCASILA dan ketentuan perundang-undangan, serta rasa kekeluargaan atau gotong-royong yang telah menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia.
Kita sudah tidak lagi dijajah seperti pada masa Pemerintahan Kolonial, namun kita jangan sampai terjajah oleh bangsa kita sendiri dan mulai untuk menghindari perilaku kuno seperti anarkis, egoisme, esklusif, dan arogansi seperti yang ditampilkan oleh para penjajah. Semoga tidak ada lagi konflik TNI dan Polri maupun konflik antar lembaga lainnya yang disikapi dengan arogansi, kekerasan, dan penyalahgunaan kewenangan. (rls)